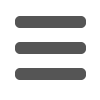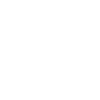Child Marriage Potret Pernikahan Dini di Pesisir Jakarta

Catatan Bang Sem
Keterampilan pembuat film pendek -- sutradara dan seluruh eksponen dan komponen pekerja kreatifnya -- dari kalangan generasi baru, kian piawai. Paling tidak, begitu kesan saya dari pengalaman sebagai mantan brodkaster televisi dan produser film dokumenter.
Kepiawaiannya terlihat mampu bertanding dan bersesanding dengan para pembuat film iklan, yang mempertimbangkan daya pesan visual tak hanya pada bilangan saat (detik), tapi sudah frame ke frame.
Wahana untuk menyajikan karya mereka di tengah dinamika media yang kian beragam medium, saluran, dan platform-nya juga kian beragam dan khas. Sebut saja reel, tiktok, youtube, dan instagram.
Banyak film-film pendek karya mereka dapat ditemukan di media sosial tersebut, khasnya youtube. Mengangkat tema tentang berbagai hal, mulai dari persoalan ekologi, ekosistem, butir-butir 17 tujuan SDG's (sustainable development goal), budaya (dalam makna yang luas), sains, teknologi, ekonomi dan bisnis (termasuk perubahan dalam industri keuangan), bahkan relasi agama dan realitas kehidupan sehari-hari yang kian kompleks.
Child Marriage produksi Mongabay Indonesia (2024), berdurasi 9:43 menit, salah satu film pendek yang menarik perhatian saya dan agaknya perlu menggugah berbagai kalangan. Khasnya pemerintah sebagai penyelanggara negara. Karena merupakan potret lain pesisir Jakarta menjelang Lima Abad dan dirancang sebagai kota Global.
Film dengan durasi pendek ini, nampak digarap dengan paduan pola kerja jurnalistik dan sinematografi yang digarap serius. Hendak menjawab pertanyaan : "Mengapa pernikahan dini masih terjadi di pesisir Jakarta?"

Kekerasan Berbasis Gender
Mengambil lokasi di Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara, yang lautnya, menurut nelayan (sumber film ini) sudah tercemar limbah pabrik dan peningkatan suhu air laut, sehingga ditinggalkan ikan sejak lama. Nelayan mengandalkan ternak kerang hijau, yang penampakannya, pun tak seperti kerang hijau di dekade 1980-an.
Film yang mengangkat isu ihwal perubahan iklim sebagai pemicu fenomena pernikahan anak di pesisir Jakarta, ini dalam durasinya yang singkat menyampaikan informasi yang kaya. Baik melalui caption, tuturan para nara sumber utama dan pendukung (sekaligus pelakon), maupun visual dengan segala atmosfernya.
Gagasan dan naskah film ini merujuk pada penelitian Ohio State University yang menemukan bagaimana dampak bencana iklim dan cuaca ekstrem dapat meningkatkan kejadian pernikahan anak. Secara global, menurut penelitian, itu diperkirakan satu dari lima anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun.
PBB mengklasifikasikan pernikahan anak tersebut sebagai kekerasan berbasis gender di kantung-kantung kemiskinan (struktural dan kultural), di mana akses penduduk terhadap modal, lemah.
Adalah Raniti, ibu dengan tiga anak: Siti, Azizah, dan Farel (yang masih balita). Siti dan Azizah disuruhnya menikah dini, seperti dia yang menikah pada usia 13 tahun.
Siti disuruhnya menikah lantaran sering sakit-sakitan. Alasannya sederhana, mengurangi beban hidup. Dengan menikah, akan ada orang yang membiayai hidup sang anak. Meski pada kenyataannya tidak demikian, karena meski sudah menikah, Siti dan anak balitanya masih menjadi beban juga. Motivasi menyuruh Azizah menikah, pun demikian.

Was was dan Santai
Azizah menikah selepas lulus Sekolah Dasar, Siti dinikahkan lebih muda dari Azizah. Usia mereka menikah relatif sama atau tak jauh dengan usia sang ibu kala menikah. Dua kakak beradik ini menjalani pernikahan dengan kesan awal yang berbeda. Siti sempat menyikapinya dengan was-was, akan halnya Azizah santai saja.
Keduanya tak menolak, karena berusaha memahami realitas kehidupan sosial ekonomi keluarganya dan termotivasi oleh kehendak meringankan beban keuangan orang tua di tengah dilema: menurunnya hasil tangkapan ikan dan meningkatnya biaya hidup.
Mimik, gestur, nada suara, dan keseluruhan performa mereka menghadirkan informasi kemiskinan yang menekan dan mereka melihat menikah di usia amat dini, merupakan jalan kebaikan. Kendati realitas rumah tangga yang dijalaninya berkata lain.
Siti menikah dengan lelaki yang berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar Rp100 ribu - Rp 200.000,- per pekan. Namun tak tentu, bergantung musim dan hasil tangkapan. Azizah menikah dengan lelaki yang berprofesi sebagai buruh. Penghasilannya tak berbeda jauh.
Penghasilan tersebut tak mencukupi, tentu. Rumah tangga mereka pun tak bisa memenuhi hasratnya untuk mengurangi beban hidup sehari-hari, tanpa kecuali untuk membayar uang sewa rumah, membeli air bersih, dan lain-lain.
Dalam situasi demikian, keyakinan, bahwa 'anak pasti ada aja rejekinya' sedemikian menguat. Dengan keyakinan itu mereka jalankan kehidupannya sehari-hari. Kendati, sering berhadapan dengan ironi. Umpamanya, kala mendendangkan lagu, "Pok Amai-amai." Karena anaknya jarang mengkonsumsi susu, selain ASI-nya yang sering kering.

Observasional
Dengan durasi sependek itu, film yang digarap sutradara Rizky Maulana Yanuar dengan dukungan reporter: Lusia Arumingtyas dan Maulia Inka Vira Faradilla, dengan editor : Harryaldi Kurniawan dan Abdillah Sitompul berhasil menyampaikan pesan realitas pahit di perkampungan miskin pesisir Jakarta itu.
Film pendek ini dibuka dengan menyajikan visual panoramis perkampungan slum yang kuat menginformasikan kemiskinan, nelayan yang menyelam dengan peralatan selam buatan sendiri (dari potongan pralon) yang riskan, perahu motor yang lusuh.
Secara visual, kerang hijau hasil panen yang segera dipipil dan kemudian dimasak secara tradisional, menggambarkan secara menyeluruh sumber pendapatan yang pas-pasan. Varian size dan sudut pandang terasa didekati dengan perspektif yang ada di benak sutradara.
Meski singkat dalam durasi, sutradara menerapkan prinsip-prinsip dasar pembuatan film dokumenter yang fokus dan jernih mengenali obyek, mengerti suasana fisik dan rasa dan mampu menganggit sisi emosi sumber (pelakon nyata). Karenanya, film ini terasa alamiah. Observasional dan pendekatan cinema vèritè.
Basis penelitian tersampaikan relatif baik, antara lain dengan pendekatan penceritaan yang menggabungkan narasi melalui caption dan tuturan pelakon. Secara sinematografi, titik pandang dan sudut pandang visual juga menarik, sutradara paham mana yang mesti menjadi fokus dengan size visual (close up, medium close up, medium shot, long shot, dan lain-lain). Hal itu nampak pada gambar anak di dalam ember, nelayan melakukan penyiapan menyelam, hasil panen kerang, proses memipil dan memasak, juga atmosfir tempat tinggal beserta tembang dangdut koplo.
Dari sisi etika, sutradara dan kru berhasil menjaga dan menghormati privasi pelakon. Para pelakon dalam film ini terkesan terbuka dan menerima keberadaan mereka dijadikan sebagai obyek, dan tak nampak dibuat-buat. Penyuntingan padat tanpa kehilangan takaran: medium, dinamis, dan kontinuiti. Bila dikembangkan dalam format 30 menit, tentu akan lebih kaya dan menggugah. Apalagi terasa fungsional dukungan editorial (Lucia Torres, Philip Jacobson, Hayat Indriyanto, Samantha Lee), Video Producer Sandy Watt, dan Asisten Produser Vincentius Budhi Prasetyo. Cag !