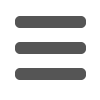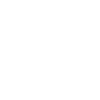Melintasi Malam di Ibu Kota Senyap

Catatan Bang Sém
Rembulan terang pada malam yang senyap. Pelataran Pagoda Uppatasanti megah yang luas, terasa sakral. Dari loudspeaker yang dipasang di beberapa sudut pagoda, terdengar suara bhiku membaca Bhagavad-gita.
Pagoda Uppasanti adalah replika Pagoda Shwedagon di Yangon, meski lebih pendek.
Beberapa gajah putih, bergerak berputar di kandangnya. Kawasan pagoda utama di Ibukota Naypridaw - Myanmar, ini menarik perhatian pengunjung. Tapi, kota ini masih sangat sepi.
Ketika kaki melangkah menaiki anak tangga, angin menyapa dengan hembusan yang halus, dari danau Marlini Mangala. Saya tak sempat menengok gambar Budha Maha Hsutaungpyae yang berada di Maha Pasadabhumi Gandhakuti, seperti diceritakan Aung Garma.

Garma juga bercerita tentang empat patung Buddha batu giok setinggi 108 kaki. Ia menunjuk ke satu arah yang terselubung remang, taman dengan 108 pohon Maha Bo dan gambar 28 Buddha. Juga tentang ruang Shin Uppagutta, ruang penahbisan Withongama (thein), dan Cetiyapala.
Ketika konsekrasi pagoda, pada 10 Maret 2009, ratusan htidaw - payung suci dikibarkan. Kuncup teratai berlian - seinbuda, juga digelar. Festival digelar di kawasan sekitar pagoda.
Berselimut malam, saya coba ingin menelusuri bulevar yang luas. Tapi, Garma mengajak saya melintasi bulevar itu dengan mobilnya. "Buka saja jendela untuk menikmati angin sejuk pengganti terik siang hari," katanya sambil tersenyum.
Kami melintasi malam, menembus senyap. Melintas di bulevar menyaksikan suasana Naypyidaw. Saya menyimak cerita Garma, ihwal negerinya, Myanmar, yang dulu bernama Burma dan pernah dipimpin U Than, tokoh bangsa yang sangat berperan dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung.

Ibu Kota negara Myanmar, ini dipandang sebagai penanda arah baru negeri itu, memasuki abad ke 21. Sebelumnya, selama lima dekade, Myanmar seolah terputus dengan dunia. Penguasa militer, kala ibu kota ini didirikan, baru saja mengendurkan tekanan dan kendali atas media, politik, dan mobilitas penduduk.
Ibu kota negara ini, semula memang kawasan belantara dengan kekayaan sumberdaya alam yang tersembunyi, teutama batu mulia. Kawasan dekat provinsi Pyinmana, 320 kilometer dari Yangon, ini sebelumnya tak bernama. Bahkan sampai tahun 2002, ketika pertama kali terbetik gagasan memindahkan ibu kota negara dari Yangon (yang dulu bernama Rangoon). Nama Naypyidaw baru diwawar pada tahun 2006.
Alasannya klasik. Ibu kota lama, Yangon sudah sangat crowded. Presiden Myanmar, Jenderal Than Shwe yang menggagas pemindahan ibu kota negara ini, benar-benar menyembunyikan alasan yang sebenarnya.
Beragam rumors berkembang, mulai dari kekuatiran perlunya pusat pemerintahan di lokasi yang dipandang paling strategis secara militer, juga alasan astrologi, alias klenik.

Rumors itu berkembang cepat, karena para petinggi negeri, itu dipandang bukan sebagai pemimpin yang rasional. Banyak hal tentang pembangunan ibukota, ini tersimpan dalam rahasia dan ketidakjelasan. Termasuk informasi kepada para negara sahabat.
Ketika Aung San Suu Kyi memimpin negeri ini, karena partainya memenangkan pemilihan umum, beberapa kali ia mengimbang kepada para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat memindahkan kantor kedutaan dan perwakilannya ke ibu kota negara yang baru ini. Tapi, sampai militer mengambil alih lagi pemerintahan, kebanyakan para diplomat asing itu bertahan di Yangon. Enggan pindah ke Naypyidaw.
"Memindahkan kedutaan besar dan kantor perwakilan, tidak seperti pindah apartemen," cetus Garma.
Proses pemindahan kantor kementerian dari Yangon ke Naypyidaw pun mengikuti nasihat para peramal. Tanggal 6 November 2005, pukul 06:37 dipandang sebagai waktu paling tepat dan menguntungkan. Maka, pada hari itu ribuan truk mulai memindahkan segala 'tetek bengek' kantor kementerian, mulai dari lemari arsip hingga perangkat kerja menteri ke ibu kota baru.
Hingga kini, proses pemindahan masih terus berlangsung. Secara fisik, ibu kota Naypyidaw memang menarik. Tak hanya karena luasnya 40 kali luas Washington, DC, yang dipenuhi berbagai gedung pemerintahan, permukiman pegawai, hotel, rumah sakit, markas tentara, bandar udara internasional, dan gedung-gedung publik besar yang indah dipandang mata. Tata ruangnya juga dirancang baik. Inilah kota megah di salah satu negara miskin yang tak henti dirundung masalah politik.

Mulanya, banyak pegawai negeri dan badan usaha milik negara yang tinggal sendiri di apartemen mereka, karena keluarganya tidak mau pindah ke sini. Kini sudah mulai banyak yang tinggal di ibu kota ini, yang masih saja terkesan lengang.
Ibu kota Naypyidaw juga terkesan fungsional, dilengkapi dengan fasilitas publik dan fasilitas sosial yang memadai, seperti sambungan internet yang cepat. Tak terkecuali kebun binatang seluas 600 hektar dan tempat rekreasi alam yang indah. Namun, karena perbandingan ruang dengan aktivitas manusia tak berimbang, tetap saja terlihat dan terasa lengang.
Penduduk lokal, non pegawai negeri, belum banyak yang tertarik tinggal di kawasan bekas hutan, ladang tebu, dan sawah ini. Maknanya, dua dasawarsa belum cukup waktu untuk 'memikat' penduduk pindah ke sini.
Ketika berkunjung ke Naypyidaw, apa yang dideskripsikan jurnalis Siddharth Varadarajan, tentang kota eks nihilo yang tidak memiliki "irama perkotaan dan ritme yang tak terduga," dan berbeda dengan kehidupan kota di Rangoon atau Mandalay.
Saya masih merasakan kesan kuat kediktatoran kartografis dari berbagai gedung yang menghiasi kota kini, termasuk markas besar partai berkuasa. Karenanya, mudah memantik dugaan, pembangunan Naypyidaw tak terlepas dari kerisauan Jenderal Than Shwe, yang kerap 'digerudug' aksi massa yang melakukan protes atas kepemimpinan militer. Ibu kota, yang oleh Miriam Berger (Washington Post) disandingkan dengan kota Oyala, yang oleh Presiden Equator Guinea - Teodoro Obiang Nguema, dijadikan sebagai pusat pemerintahan yang 'tak terjangkau' oleh rakyat yang menentang dan menantang pemerintahannya. Nguema memaksakan diri membangun Oyala, meski dia tahu, lebih dari separuh rakyatnya, hidup di bawah garis kemiskinan.

Dugaan (kota yang dibangun sebagai ekspresi paranoid penguasa) semacam itu wajar, karena Yangon tak pernah henti oleh gerakan aksi massa rakyat. Antara lain aksi Pemberontakan 8888 pada tahun 1998) dan Revolusi Saffron 2007 terhadap pemerintah militer nasional Myanmar.
Naypyidaw - sebagaimana tercermin dari bentuk bangunan dan pola tata ruang zona pemerintahannya -- tidak karib dengan proses demokratisasi yang sedang terus mencari jalan menemukan format idealnya. Di ibu kota ini, siapapun akan merasa memasuki kawasan yang menjadi persemaian kecurigaan.
Aksi pengambil alihan kekuasaan oleh militer tahun 2021, selain membalik harapan akan berlangsungnya demokratisasi yang mulai menggeliat, kian menampakkan kesan, bahwa Naypyidaw dibangun untuk tujuan khas penguasa. Menjadi isolasi spasial penguasa dengan menebar banyak para 'mata-mata.'
Melintas malam atau 'keluyuran' siang hari di ibukota senyap Naypyidaw, 'tekanan suasana' memang sangat terasa. Walaupun di lingkungan hotel, para pelayan bersarung, melayani dengan ramah. |
Artikel terkait: Ibu Kota Masih Jadi Kota Hantu | Istana Megah Menanti Suu Kyi di Kota Sunyi | Menyimak Samboja - Sepaku, Membayangkan Naypyidaw |