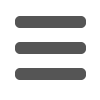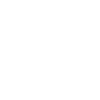Ronggeng Dulu dan Setelahnya

Endang Caturwati
Berbicara mengenai perempuan sangatlah kompleks, setiap daerah setiap kelompok memiliki nasib serta kondisi yang berbeda. Begitu pula dengan perempuan dalam seni pertunjukan.
Citra perempuan dalam seni pertunjukan di manapun berada pernah membuat batas pemisah antara perempuan berpendidikan dan perempuan kebanyakan. Suatu fenomena ( sebelum tahun 1950-an ) di Jawa Barat, khususnya di wilayah Priangan dalam kurun waktu tertentu, perempuan terpelajar dan perempuan dari kalangan ménak tidak boleh tampil di pertunjukan umum karena selalu diidentikkan dengan ronggéng.
Ronggéng merupakan tari hiburan seperti dombrét, belentuk ngapung, dogér kontrak, dan ketuk tilu atau ronggéng di arena tayuban, yang di masyarakat secara struktur sosial dipandang mempunyai konotasi negatif layaknya perempuan penghibur atau identik dengan pelacur, seperti diungkap Raffles dalam The History of Java (1817),
Berkat perjuangan seorang ménak (bangsawan) asal Banten T.B. Oemay Martakusuma, pada awal dekade 1950-an di wilayah Priangan Jawa Barat, perempuan terpelajar dapat tampil di tempat umum menarikan tari kreasi karya Tjetje Somantri yang bersumber dari tari Jawa klasik.
Tariannya kemudian menyebar, selain ditarikan sebagai ajang seni pertunjukan di Istana Negara, juga di berbagai mancanegara. Selain itu, kemudian, tariannya juga diajarkan di sekolah-sekolah dan menjadi materi tari di setiap festival ataupun pasanggiri tari sebagai kelompok ‘tari Sunda klasik’ atau ‘wanda klasik’.
Perempuan yang tampil dalam seni pertunjukan di mana pun berada pada masa lalu ternyata mengundang pro dan kontra, serta mendapat penilaian yang sama, lebih banyak dikaitkan dengan perilaku negatif yang konotasinya mengarah pada prostitusi dan marginalisasi.
Citra tersebut melekat pada kurun waktu yang lama, bahkan sebagian masyarakat, masih ada saja yang menyebut penari di Jawa Barat ibarat ‘kembang buruan’ atau bunga liar, yang dapat dipetik oleh sembarang orang.

Citra Ronggeng pada Masyarakat Sunda
Ronggéng di Jawa Barat pada masa lalu merupakan sosok perempuan terhormat sebagai Syaman dalam upacara-upacara ritual, yang kemudian tergeser sejak masuknya Agama Islam pada tahun 1551. Sebagian pengikut Agama Islam tidak mengakui peran perempuan sebagai pemimpin (Nursaid, 2005).
Sosok ronggéng kemudian muncul kembali sejak hadirnya peradaban Barat dengan berkembangnya budaya perkebunan, yang merekrut tenaga kuli-kuli kontrak serta perempuan buruh pribumi di perkebunan-perkebunan, khususnya perkebunan kopi yang ditanam di tanah-tanah hutan yang belum dibuka di daerah Priangan yang ditetapkan Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada tahun 1707 (Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991) dengan kedudukan serta fungsi ronggéng yang berbeda, seiring dengan perubahan masyarakat pendukungnya.
Dengan adanya perkebunan di wilayah Indonesia yang merekrut para kuli serta mendatangkan para pekerja dari Eropa yang pada umumnya masih perjaka, maka berkembang adanya pergundikan, pelacuran, serta pertunjukkan hiburan yang menyajikan penari hiburan yang disebut ronggéng.
Dengan berkembangnya budaya perkebunan, yang merekrut tenaga kuli-kuli kontrak serta perempuan buruh pribumi di perkebunan tatar Sunda Jawa Barat, menjadikan adanya peradaban baru.
‘Peradaban Barat’ yang sama sekali merupakan zaman baru dalam kehidupan budaya Indonesia yang bersifat sekular, rasionalistik, dan empirik. Sementara peradaban Indonesia sebelumnya bersifat spriritual dan mistis.
Dalam hal ini, karena kebanyakan mereka datang ke Indonesia sebagai fortuin zoekers, pencari harta, trekkers (pengembara) dan tidak menjadi blijvers (penetap). Sifat sementara ini sangat mempengaruhi gaya hidupnya, lebih-lebih dalam soal etika dan moral.
Tambahan pula dalam masyarakat frontier, individualisme tidak terkendalikan dan mudah menjurus ke liberalisme, khususnya dalam hubungan seks yang dapat menimbulkan promiskuitas.
Adanya hiburan pesta ronggéng, kendatipun para kuli kontrak telah bekerja keras, namun uangnya selalu habis, selain untuk menyawér juga melacur, minum, berjudi, dan menghisap candu (Kartodirdjo dan Suryo , 1991).

Ronggéng ada di mana-mana, merupakan fenomena budaya yang banyak disinggung dalam berbagai tulisan. Antara lain Kidung Sunda, sebuah karya sastra Jawa Tengahan yang ditulis sekitar tahun 1500-an; Serat Centhini (1814) karya sastra Jawa terkenal yang berupa tembang, serta tulisan-tulisan karya penulis asing yang pernah mengamati kondisi budaya di Indonesia antara lain, yaitu Thomas Stamford Raffles dalam bukunya yang berjudul The History of Java (1817), Claire Holt dengan karyanya berjudul Art in Indonesia: Continuities and Change (1967), P. J. Zoetmulder dalam bukunya Old Javanese-English Dictionary (1982), Peter Boomgaard dengan tulisannya bertajuk Children of The Colonial State: Population Growth and Economic Development In Java 1795-1880 (1989), serta Henry James Spiller dalam disertasinya berjudul Erotic Triangles: Sundanese Men’s Improvisational Dance in West Java Indonesia (2001).
Thomas Stamford Raffles seorang Letnan Gubernur Inggris yang pernah berkuasa di Jawa pada tahun 1811 sampai dengan 1816 dalam bukunya The History of Java (1817), menulis tentang ronggeng, sebagai berikut. "…the common dancing girls of the country…are called ronggeng, are generally of easy virtue. They make a profession of their art, and hire themselves to perform on particular occasion, for the amusement of the chiefs and the public. Though to be found in every principal town, their performance is most highly esteemed in the western, and particularly among the mountaineers of the Sunda districts, where the superior graces of the bedaya are unknown…. Their conduct is generally so incorrect, as to render the title of ronggéng and prostitute synonimous…."
Dalam tulisannya ini, Raffles mengungkapkan tentang perempuan penari yang disebut ronggèng. Dengan profesi seninya, mereka tampil pada kesempatan tertentu untuk menghibur para petinggi dan khalayak. Kendati bisa ditemukan di setiap kota utama (di Jawa), di Jawa Barat - khasnya di desa-desa kaki gunung di wilayah Sunda, pertunjukan mereka mendapat tempat khas. Masyarakat di daerah ini, tak mengenal tari bedaya dengan pesonanya yang agung. Tingkah laku para ronggéng, menurut Raffles, secara umum menyimpang, sehingga istilah ronggéng dan pelacur adalah sinonim.
Akan halnya Hesselink, melihat dengan cara pandang lain. Menurutnya, ada perlakukan istimewa kepada ronggéng Sunda dari para penguasa Pemerintah. " Although ronggéng were regarded as seks worker, government powers generally treated them differently from “ordinary” prostitutes. When prostitutes was regulated in Java, ronggeng were subject to mandatorymedical examinations: they were not taxed like otherprostitutes, however," tulis Hesselink (1992).
Hesseling mengungkapkan pandangannya, kendati ronggéng dianggap (sama) sebagai pekerja seks, namun para penguasa - petinggi pemerintah pada umumnya memperlakukan mereka secara berbeda dari pelacur "biasa".
Ketika pelacur diatur di Jawa, ronggeng diwajibkan menjalani pemeriksaan medis: mereka (juga) tidak dikenakan pajak seperti pelacur lain.

Para ronggéng pada umumnya disanjung oleh penduduk dan tidak jarang pula, karena penampilannya yang sangat memukau, beberapa ronggéng bahkan disunting oleh ‘pejabat rendahan’ dan 'raja.' Hal ini merupakan nasib baik bagi si ronggéng.
Di Cirebon, misalnya. Banyaknya pertunjukan yang menampilkan ronggéng pada acara-acara pesta atau hiburan, menginspirasi Sultan untuk mendirikan sekolah ronggéng yang langsung berada dalam perlindungannya (Peter Boomgaard, 1989).
Namun demikian, pada kenyataannya, selain dipuja sosok ronggéng sering pula dilecehkan oleh para pengibing (penari spontan) lelaki hidung belang yang tidak tahan menahan hasrat nafsu birahinya, dengan memasukkan uang ke dalam kemben sambil meremas buah dada di depan umum (suwelan).
Bahkan, menurut Miftahus Surur (2003), tak jarang juga terjadi, wajah ronggéng dipukul pengibing yang sedang mabuk berat di arena pertunjukan, manakala ia dianggap tidak mau melayani hasrat laki-lakinya.
Dalam ensiklopedi Sunda disebutkan, di daerah Jawa Barat pada masa sebelum perang (sebelum kemerdekaan tahun 1945) semua perempuan yang menyanyi atau menari di depan umum dan melayani penonton dengan imbalan uang, seperti ketuk tilu, dogér, dombrét, longsér, dan lain-lain disebut ronggéng.
Penonton yang tertarik kepada seorang ronggéng, biasanya sering lupa diri. Oleh karenanya sering terjadi keributan, baik pada waktu pertunjukan atau sesudahnya, hanya karena memperebutkan ronggéng (Ayip Rosidi, et al., 2002).

Ronggéng, Pajak, dan Denda Nawala Pradata.
Keributan karena perkara ronggéng, pada masa kolonial justru dijadikan ajang komoditi. Terlebih di wilayah Batavia, Bogor, dan Priangan, ronggéng telah menjadi hiburan primadona, khususnya bagi para buruh kuli di areal perkebunan. Bahkan sejak awal tahun 1706, ronggéng telah menjadi sumber pendapatan bagi penguasa Belanda dengan pwmungutan ‘pajak ronggéng’ secara resmi oleh komisaris urusan pribumi.
Pada tahun 1789, menurut Peter Boomgaard (2004), pemungutan pajak ronggéng ini disahkan oleh penguasa Belanda, yang bukan hanya dari penghasilan ronggéng, tetapi juga ‘pajak hiburan’ bagi ‘penyelenggara’ pesta ronggéng (hajatan yang menanggap hiburan ronggéng) yang dipungut oleh para bupati.
Dengan demikian dari pertunjukan ronggéng saja, penguasa Belanda telah mendapat tiga sumber pendapatan, yakni, dari ronggéng, hiburan ronggéng (grup pertunjukan ronggéng), dan dari penyelenggara pertunjukan ronggéng (penanggap).
Adanya pesta ronggéng hingga ke pelosok-pelosok daerah tersebut sering memicu keonaran, hingga para penguasa Jawa maupun Belanda mengeluarkan peraturan untuk mencegah kekerasan yang sering terjadi selama pertunjukan ronggéng. Mereka yang terlibat dalam kekerasan, didenda berupa ‘Nawala Pradata’.
Denda ini, menurut Boomgaard (2003), diatur dalam ketentuan yang ‘wajib’ dikenakan bagi para pelaku kejahatan bila terjadi keonaran, yang mengakibatkan ada korban terluka atau terbunuh.
Para pelaku kejahatan tersebut dikenakan denda berupa sejumlah uang dengan nilai yang tinggi bagi mereka yang mampu, sedangkan bagi orang miskin, dikenakan denda fisik berupa pukulan ‘gebuk.’
Oleh karena seringnya terjadi keonaran pesta ronggéng yang meresahkan masyarakat, akibatnya pada tahun 1778 dikeluarkan ‘larangan pesta ronggéng’ tanpa adanya persetujuan dari pemilik perkebunan yang berkembang di sekitar daerah Batavia dan kabupaten Bogor.
Larangan ini diberlakukan, khususnya di tempat para kuli yang keras kepala, yang bekerja di perkebunan swasta sebagai tenaga upahan yang selalu menghabiskan uangnya hanya untuk mengonsumsi minuman keras, berjudi, menghisap candu, dan melacur.
Pada tahun 1880, larangan ini diberlakukan pada semua perkebunan. Namun demikian, menurut Boomgard (2004) pada tahun 1887 dikenakan peraturan baru, yaitu beberapa pengecualian untuk tetap mengadakan pertunjukan ronggéng bagi beberapa perkebunan untuk mengikat terjadinya para buruh atau kuli kontrak meninggalkan areal perkebunan.
Terlepas dari perilaku ronggéng yang pada umumnya lebih cenderung menggambarkan sosok perempuan penghibur, baik di luar panggung, maupun dalam konteks pertunjukan yang selalu membuat keonaran, pada kenyataannya sosok ronggéng begitu kompleks dan tidak hanya sebatas sebagai perempuan penghibur di arena kalangenan saja.
Semua yang terjadi merupakan proses akibat situasi dan kondisi sosial yang tidak dapat dipungkiri. Akan tetapi dalam perkembangan perjalanannya, menurut Ineke Zweers (1989), ronggéng mempunyai arti penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat, khususnya sebagai perempuan terhormat dalam upacara-upacara ritual, baik sebagai syaman, atau pun sebagai seseorang yang memiliki kemampuan khas (daya luwih) yang pada usia tuanya sering dimintai petuah dan nasihat.

Perubahan Citra Ronggeng
Hiburan ronggéng tidak hanya berkembang di kalangan rakyat atau kuli perkebunan saja. Sekitar tahun 1920-an ronggéng sering menyemarakkan arena tayuban para kaum ménak, sehingga pada kurun waktu tertentu para perempuan terpelajar ataupun dari kalangan ménak, dilarang untuk mempertontonkan diri di arena pertunjukan, karena selalu diidentikan dengan ronggéng.
Dengan hadirnya Tjetje Somantri kreator tari Sunda yang mengembangkan tari perempuan dari sumber gerak tari Jawa pada sekitar awal tahun 1950-an, baru kemudian perempuan terpelajar khususnya kalangan ménak dapat tampil di tempat-tempat pertunjukan.
Perubahan pandangan tentang seni tari sekaligus keinginan mengangkat derajat perempuan terus berlangsung. Kiprah Tjetje Somantri, di bawah bendera Badan Kesenian Indonesia (BKI) pimpinan ménak Sunda asal Banten Tubagus Oemay Martakusumah dapat mengangkat citra ‘perempuan penari’ di papan atas. Tariannya kemudian dikenal hingga ke berbagai mancanegara dengan ciri khas tarian yang gemulai bergaya klasik (Endang Caturwati, 2000).
Sosok Ronggéng masih terdapat pada berbagai pertunjukan hiburan hingga masa kini, antara lain Kliningan Bajidoran di daerah Subang, Ronggéng Gunung di daerah Ciamis, Banggreng pada pertunjukan Tayub di Sumedang, Ronggeng Kedempling di daerah Majalengka.
Masing-masing pertunjukan mempunyai tata cara yang berbeda, namun masih tetap dengan saweran uang dari para penonton.
Bedanya pada masa kini yang memberi saweran berupa uang tidak hanya laki-laki, perempuan pun banyak yang nyawer, serta lebih tertib, dan jarang terjadi adanya keributan.
Biasanya mereka ditanggap pada acara-acara pesta pernikahan atau ulang tahun Lembaga, atau Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Ronggeng sebagai 'indung'
Ronggeng masih berkembang di daerah Jawa Barat, pada pertunjukan hiburan di daerah Subang, Karawang, Ciamis, dan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat.
Baik Sunan Ambu, maupun dan Dewi Sri pada kenyataannya hanyalah legenda yang masih dipercaya sebagai simbol perempuan Sunda , sosok Ibu atau indung yang punya kharisma. Sedangkan ronggèng masih terdapat di alam nyata.
Fenomena yang paling penting, adalah sebagai seorang ’indung,’ mempunyai tanggung jawab yang besar, pada masa depan anak-anaknya.
Apapun predikat yang disandangnya, pada kenyataaanya sebagaian besar para ronggéng memikul beban, harus memelihara anak-anaknya akibat perceraian. Karena pada umumnya, laki-laki yang pernah mengawini ronggéng, tidak pernah mempedulikan kelangsungan kehidupan anak-anaknya.
Sejumlah pakar berpendapat, kebutuhan pertama dan utama bagi seorang anak adalah kebutuhan akan kelekatan (attachment), terutama kelekatan dengan ibunya (maternal attachment).
Hal ini sangat diperlukan, karena ibu dapat memberikan rasa aman, stabilitas, dan predictability (Yudit Schickendanz, 1995).
Apabila rasa aman terbentuk, maka rasa percaya dan perasaan diri anak akan berkembang dengan baik. Ibu menguasai posisi sentral secara emosional.
Tokoh Sunan Ambu, Shangyang Sri dan Ronggéng merupakan tokoh-tokoh perempuan yang mempunyai kedudukan mulya, merupakan ’sosok indung’ pemberi kehidupan serta kedamaian bagi umat manusia.
Dalam konteks pertunjukan, ronggéng pun telah memberi kehidupan dengan menjadikan sumber pendapatan bagi berbagai pihak. |
Prof. Dr. Endang Caturwati, ST, MS. adalah Guru Besar Ilmu Seni Pertunjukan - Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) - Bandung.