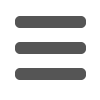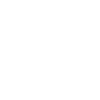Demokrasi Palsu dalam Arus Politik Global

Bang Sém
Demokrasi tak kan pernah usai dibincangkan dari masa ke masa. Para akademisi dan guru besar ilmu politik pun akan terus berkutat 'mencari ketiak ular,' di jalan katarop pemikiran politik yang berujung pada kuldesak.
Entah sampai bila, krisis politik diteliti dan dibincangkan, dan tak ada sesiapapun yang mampu menahan krisis atas sistem tata kelola masyarakat, negara, dan bangsa 'yang terbaik di antara yang terburuk,' itu. Apalagi, ketika mereka yang mengendalikan politik praktis, dari masa ke masa terus mengalami penurunan kualitas, dari negarawan hanya menjadi politisi dan petinggi.
Lebih empat tahun lalu, mantan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Kofi Annan dalam ceramahnya di Forum Demokrasi Athena (13/9/17), setahun sebelum wafat, mengingatkan. Ia mengutip pendapat abadi Aristoteles yang tak terbantahkan sepanjang 2000 tahun, bahwa "Manusia pada dasarnya adalah hewan politik."
Manusia lahir, hidup dan mati sebagai anggota komunitas dan urusan komunitas itu adalah miliknya dan sebaliknya. Dalam konteks menyikapi sententia aeterna Aristoteles, yang kemudian menjadi adagium, itu banyak kalangan yang kadung dijuluki sebagai pejuang demokrasi tanpa lelah, semacam Annan, tak pernah usai memperjuangkan demokrasi.
Mereka terus menerus yakin, bahwa demokrasi adalah sistem politik yang paling kondusif untuk perdamaian, pembangunan berkelanjutan, supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tiga pilar masyarakat yang sehat dan demokratis.

Mendiang Annan dan banyak pejuang demokrasi, termasuk Larry Diamond, Economist Intelligence - Freedom House, meyakini, bahwa kemerdekaan demokratis telah mundur selama sebelas tahun berturut-turut di banyak bagian dunia, semakin banyaknya pemerintahan otoriter terpilih. Bahkan melalui sistem demokrasi.
Demokrasi terus menerus mengalami krisis kepercayaan. Tidak hanya karena menghadapi lawan yang semakin tegas, tetapi karena semakin banyak penerima manfaat demokrasi, menerima begitu saja realitas politik, dan kemudian meragukan manfaat demokrasi itu sendiri.
Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi demikian. Salah satunya adalah berlangsungnya krisis tak berkesudahan, mulai dari krisis ekonomi, moneter, budaya (termasuk spiritual dan religi), keadilan dan kemanusiaan yang menebar krisis identitas kebangsaan.
Rontoknya tembok Berlin pada dekade 1980-an yang dirayakan sebagai kebangkitan ulang demokrasi, sejak awal sudah dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha berkuasa, semacam George Soros, menebar racun oligopoli lewat pilantropi politik dan kapitalisme global.
Annan menilai, pergeseran persepsi dan praktik demokrasi -- bahkan di tempat mana demokrasi dilahirkan dan berkembang sebagai sistem politik dunia -- telah ditandai dengan berkembangnya apatisme menyertai pragmatisme politik dan politik transaksional. Pun, longgarnya keanggotaan partai politik yang menurun, bersamaan dengan merosotnya kepercayaan yang menurun pada politisi dan institusi politik.

Populisme palsu terus disemai dan dipelihara oleh oligarki politik dan oligopoli ekonomi, melalui beragam institusi keuangan dan moneter internasional. Lantas berhadapan dengan sosialisme mondial yang diubahsuai dengan komunisme baru: kapitalisme berjubah sosialisme - populisme.
Dalam situasi demikian, tak ada institusi politik palagi di negara-negara yang sedang menghabiskan waktu dan energi -- sejak dekade 70-an -- terjebak dalam friksi dan konflik politik tak berkesudahan. Bahkan, belakangan hari, tampil dalam dramatika konflik ideologi tanpa dramaturgi politik yang jelas.
Tak banyak bangsa dan negara yang menyadari realitas ini, kecuali Republik Rakyat China yang sejak awal merespon perubahan orientasi mondial dari Amerika - Eropa ke Asia Pasifik. Kesadaran yang lantas memantik kesadaran Amerika Serikat dan sekutunya untuk terjaga dari tidur malam usai 'pesta gemerlap' demokrasi kala kapitalisme meremas dunia dalam genggaman kekuasaan.
Antara lain dengan melahirkan para aktor yang seolah-olah merupakan para pemimpin kharismatik dan ratu adil, bahkan nabi-nabi palsu di tengah demokrasi yang macet.
Para binatang politik, seperti yang dikemukakan Aristoteles, menebar kerisauan Machiavelli, Karl Marx, dan berbagai pemikir lainnya, untuk menahan para pemikir kemudian terjebak di masa lalu dan terengah-engah mengikuti proses cepat perubahan bangsa.

Khalayak di berbagai penjuru dunia, lalu terseret arus pandang demokrasi a la Samuel Huntington di sela rabaan John Naibitt tentang global paradox dan Alvin Toffler tentang future schock tentang masa depan yang remang dan gelap.
Para akademisi di berbagai belahan dunia, khasnya di berbagai negara berkembang, tak merespon baik isyarat-isyarat Naisbitt dan Toffler, lalu sibuk merujuk aneka pemikiran yang kait berkait. Bahkan lambat merespon isyarat-isyarat lebih segar yang ditawarkan Jared Diamond, tentang konflik politik yang terus meluas akibat ketidak-mampuan mengelola sumberdaya alam. Pun abai memahami warning Cioran ihwal gerak besar perubahan dari agriculture ke paradox.
Termasuk abai atas isyarat mutakhir yang dilontarkan tokoh revolusioner Oxford University, James Martin (2012) tentang singularitas yang terkoneksi langsung dengan internet on think dan menjadi pintu masuk penyebaran hoax dan fake information, kemiskinan, pandemi global (biowarfare), migrasi global, transhumanisma, petaka demografi, keperluan mendesak akan nanoteknologi sebagai bagian artificial intelligent, gerakan besar aktor non negara, dan lainnya yang menjadi tantangan sekaligus ancaman abad ke 21. Padahal, sebelumnya, George Musser sudah meneriakkan Climax of Humanity (2005).
Abad ke 22 menjanjikan era kegelapan atau jaman jahiliyah baru, bila sejak paruh pertama abad ke 21, persoalan-persoalan asasi yang menimbulkan kegamangan, ketidakpastian, keribetan dan kemenduaan, termasuk ambivalianisme sosio budaya. Termasuk bergeraknya generator sociocapitalism menggerakkan populisme palsu demokrasi sungsang.
Kelengahan terhadap berbagai isyarat dan peringatan para pemikir futurist dengan tawaran-tawaran socio imagineering untuk terus memelihara dan menghidupkan optimisme sebelum dunia lantak oleh berbagai kutukan zaqman kiwari, seperti pandemi global nanomonster Covid-19, akan menghadapkan banyak negara terjerembab ke lembah nista, karena tak lagi punya nation dignity dan tak mampu mengangkat tonggak global nationalism.

Annan menyebut, demokrasi akan menemukan jalan petaka, ketika ketimpangan di dalam negara meningkat dan memperlihatkan tidak meratanya manfaat globalisasi bagi pemenang dan pecundang dalam dinamika demokrasi politik internal yang tak mampu membebaskan diri dari oligarki.
Ketika itu, menurut Annan, pasar global menciptakan miliarder, sementara pendapatan kelas menengah dan pekerja di negara maju mengalami stagnasi dan mata pencaharian mereka menjadi semakin rentan terhadap perubahan teknologi dan persaingan global. Dan di negara-negara berkembang, rakyat menjadi kuli di tanah airnya sendiri.
Ketidaksetaraan yang semakin parah, menurut Annan, tersebabh oleh pasar keuangan yang semakin terintegrasi telah memungkinkan para pemenang globalisasi untuk memarkir keuntungan mereka di surga pajak, sementara beban pajak pada kelas menengah terus meningkat. Ketika kekayaan terlalu terkonsentrasi, pemerintahan amat sangat tak berdaya dipermainkan oligarki.
Dalam situasi demikian, dari berbagai teori yang berkembang mutakhir, sociocapitalisme yang dipelopori China akan berjaya, karena kapitalisme global dan sosialisme mondial tak lagi memberikan nafas. Khasnya pada munculnya solusi arus baru pemikiran universe prosperity yang lama tersimpan dalam ajaran agama samawi, khasnya Islam. Terutama karena pemimpin dan pemuka agamanya, sibuk mengurusi isu-isu praktis dan tak mampu membebaskan diri dari konflik sektarian.

Penelitian mutakhir Prof Martin Gilens - guru besar ulung Universitas Princeton dan Prof Benjamin - guru besar ulung Universitas Northwestern dengan analisis multivariat menunjukkan bahwa elit ekonomi dan kelompok terorganisir yang mewakili kepentingan bisnis memiliki kuasa oligarki, merampas independensi secara yang substansial terhadap kebijakan pemerintah (dimulai dari Amerika Serikat), akan halnya rata-rata warga negara dan kelompok kepentingan berbasis massa, hanya memiliki pengaruh sedikit atau tidak ada berpengaruh dalam mengelola independensi yang disyaratkan demokrasi.
Gilens dan Benjamin mengemukakan, orang Amerika memang menikmati banyak fitur yang penting bagi pemerintahan demokratis, seperti pemilihan umum reguler, kebebasan berbicara dan berserikat, dan hak pilih yang tersebar luas (jika masih diperebutkan). Tetapi keduanya tak percaya, akankah negara bangsa yang dipimpin Joe Biden, itu masih menjadi penggerak demokrasi, jika oligarki menguasai pemerintah
Demokrasi Amerika akan menjadi demokrasi palsu, tidak peduli berapa banyak yang dipompa oleh oligarki yang menjalankan negara dan yang mengontrol media "kabar" bangsa, ungkap Eric Zuess (Counterpunch, 2021). Dia menyebut, Amerika Serikat, dengan kata lain, mirip dengan Rusia atau sebagian besar negara 'demokratis' 'pemilihan' lainnya yang meragukan.
Sejumlah negara -- terutama yang tergabung dalam G20 -- termasuk yang dikemas lembaga moneter dan bank dunia, diprediksi akan 'terlena' dan tak segera sadar menahan diri untuk tidak mengalami nasib laiknya Argentina, Al Jazair, setara Ukraina, menjadi 'keledai politik global' di tengah arus demokrasi yang kian rapuh. Dinina-bobokan oleh buaian populisme palsu dalam praktik otoriterian berjubah demokrasi. Bagaimana dengan Indonesia dan Malaysia? Wallahu a'lam bissawab.|