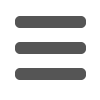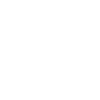Cuma Opera Sabun

STEVEN Pressfield menerbitkan bukunya bertajuk War of Art. Penulis Amerika yang fokus pada penulisan fiksi sejarah, non fiksi, dan skenario sinetron berusia 74 tahun, itu jebolan Universitas Duke. Dia lahir pada September 1943 di Port of Spain – Trinidad.
Sebelumnya, Pressfield menulis dan menerbitkan buku bertajuk: The Legend of Bagger Vance , Above the Law, King Kong Lives, Joshua Tree, Freejack dan Separate Lives.
War of Art menjadi semacam ‘baku panduan’ tentang peperangan rohani. Di buku ini, diulas taktik melipat perlawanan, melalui suatu eksplorasi kekuatan ‘jahat’ untuk mencegah berlangsung kebajikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Bagian menarik buku ini adalah bab ihwal Perlawanan dan Dramatisasi diri (termasuk juga sosial).
Pressfield menulis: menciptakan sandiwara dalam hidup adalah wahana menghidupkan kesan perlawanan (untuk kemudian dilipat begitu rupa, supaya perlawanan itu sirna). Dalam konteks dramatisasi, anasir-anasir utama keluarga boleh dilibatkan, khasnya untuk mendapatkan kesan umum: perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perlawanan, melalui aksi persekusi.
Sandiwara bisa diciptakan di mana saja dan untuk tujuan apa saja, termasuk tujuan politik. Terutama ketika aksi simpatik yang dibungkus dengan kemasan amal sosial, berakhir buruk dan memakan citra yang hendak dibangun.
Sandiwara politik harus diciptakan dalam waktu yang singkat dari peristiwa sebelumnya, supaya perhatian berubah. Caranya, menciptakan adegan seolah-olah berlangsung aksi massa perlawanan yang berhadapan satu sama lain di ruang publik.
Setting karakternya adalah ruang publik. Format konfliknya: friksional, supaya tak terjadi korban dalam jumlah besar, karena keperluannya hanya mengesankan, bahwa aksi perlawanan sosial terhadap rezim, adalah buruk, dan berakibat buruk, baik terhadap sosial ataupun ekonomi.
Dalam konteks sandiwara begitu, diperlukan aktor dan aktris cempeng saja, supaya biayanya rendah. Ambil saja perempuan dan anak-anak yang harus dikesankan menjadi korban tekanan dari barisan perlawanan.
Dalam masyarakat melodius dan pendek akal, adegan itu akan bersambut. Lantas eksplorasi melalui media sosial, sehingga memancing (atau memang disiapkan) para ‘pelapor’ media mainstream, meliput berjam-jam dan menayangkannya berulang-ulang.
Kerahkan juga mereka mewawancarai petinggi negeri, pengamat politik, atau akademisi dengan pikiran instan dan logika cekak.
Adegan akan viral dan aksi perlawanan yang disiapkan dalam sandiwara, akan menjadi pusaran yang diharapkan dapat melipat perlawanan yang sesungguhnya.
Menyimak trend isu akhir pekan (yang memang sepi sensasi) sejumlah media mainstream, khasnya televisi, melakukan eksplorasi dengan teknik penayangan re run berulang-ulang, peristiwa yang setting format-nya, mirip format opera sabun kelas tertier.
Kali ini, propertinya adalah kaos, adegannya jalan gembira, dramatisasinya: bipolar, aktornya : masyarakat amah tak beridentitas (kecuali yang mengenakan kaos). Target: ‘melipat perlawanan.’
Sayangnya, aktor dalam adegan yang kemudian diviralkan, itu tak mengikuti alur standar: ricing action, action, klimaks, dan anti klimaks. Karena alurnya tak jelas, sandiwara pun menjadi tak jelas. Apalagi terjadi lompatan, langsung ke anti klimaks. Dialognya menggunakan istilah-istilah baku: sistemik, terencana, persekusi, intimidasi, massif dan intoleran – anti demokrasi. Yeahhh !!
Tentu, bagi sebagian kalangan dengan selera tontonan apa saja, sandiwara ini menarik perhatian, lantas akan berkembang berhari-hari. Sebagian orang lain, juga akan menarik sandiwara itu ke dalam gunemcatur – temu bual – sembang-sembang alias ngobrol kedai kopi.
Sebagian terbesar lainnya dengan kecerdasan prima dan punya nalar tajam, tentu akan terkekeh bersama-sama. Karena sandiwara yang hendak dibikin dramatik, itu berubah performanya, menjadi komedi slapstick.
Tentu, sandiwara itu tak akan mampu menghela gelombang lebih besar yang akan datang kemudian sebagai suatu gerakan sosial yang nyata : aksi buruh menuntut penolakan terhadap tenaga kerja asing (kasar) dari Tiongkok, perlawanan terhadap upah buruh yang rendah, kegamangan bank sentral melakukan intervensi untuk memperkuat rupiah yang sempat tembus Rp14.000 / 1USD.
Sandiwara yang buruk tak akan merasuk ke dalam minda khalayak luas dan tak akan mempengaruhi sikap untuk mengurangi dan menyurutkan perlawanan. Karena satu-satunya yang bisa menyurutkan perlawanan sosial, hanya kemampuan prima (siapa saja yang berkuasa) memenuhi janji politik mereka.
Rakyat tak perlu sandiwara, karena yang mereka perlukan hanyalah : tersedianya pangan – sandang – papan yang cukup dan terbeli, tersedianya lapangan kerja dan lapangan berusaha (penguatan akses rakyat kepada modal, pasar, dan informasi benar), kuatnya akses dengan ekstensi kesehatan dan pendidikan, berlangsung proses transformasi birokrasi berorientasi pelayanan. Selain itu adalah aman nyamannya rakyat menjalankan ibadah dan kehidupan primer sehari-hari.
Rakyat tak perlu sandiwara, karena yang mereka perlukan adalah realitas pertama kehidupan yang langsung mereka rasakan manfaatnya.
Apalagi sekadar sandiwara yang didesain bukan oleh desainer yang hebat, dan tak didukung oleh aktor dan sutradara yang paham dramaturgi politik.. Maksud hati menghadirkan sandiwara tragedi, apa daya hanya jadi opera sabun komedi slapstick.|