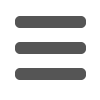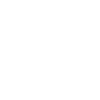Sabdo Pandito Rakjat, Memotret Kegaduhan Bangsa
AKARPADINEWS.COM | KELOMPOK seni wayang Ki Sabdo Tedjo tengah sepi tawaran pementasan. Sekalinya dapat tawaran, datang dari keluarga miskin. Sepasang suami istri dari kelas papa itu ingin kelompok itu mementaskan wayang untuk meruwat anaknya. Atas permintaan itu, Ki Tedjo tak langsung mengamini.
Dia mendiskusikannya terlebih dulu dengan para anggota kelompok seninya. Soal berapa keuntungan yang didapat dari pementasan, menjadi bahan perdebatan. Sebagian besar anggota kelompok ingin, setiap pementasan wayang harus memberikan keuntungan.
Mendengar keinginan anak buahnya itu, Ki Tedjo dengan bijak mengingatkan jika mereka adalah seniman, bukan artis. Ki Tedjo lalu menceritakan tentang kisah Ki Nartosabdo, dalang kondang yang mau mendalang tanpa bayaran, untuk membantu orang lain yang ingin menggelar ruwatan.
Di sela-sela diskusi, datang Pak Surya, seorang pengusaha kaya raya. Dia datang sembari membagikan uang kepada para anggota kelompok seni Ki Tedjo. Lalu, Surya menasehati Ki Tedjo jika zaman sudah berubah sehingga petuahnya dianggap tak lagi sejalan dengan perubahan zaman. “Kalau petuah-petuah kosong sudah tidak zamannya,” nasehat Surya. Harta, lanjut Surya, yang utama.
Mendengar itu, Ki Tedjo membalas. Menurutnya, harta bukan hal yang utama dalam kehidupan ini. Sebab, seseorang bisa hidup tanpa harta. Ki Tedjo kemudian mengutip pepatah Jawa yang didengungkan RM Pandji Sosrokartono dan Ki Ageng Suryomantaram, yakni sugih tanpa bandha, digdaya tanpa aji, trima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajrih, langgeng tanpa susah, tanpa seneng, dan anteng mantheng sugeng jeneng. “Pilih jenang apa jeneng, pilih harta apa nama?” ucap Ki Tedjo dengan nada rada tinggi pada Pak Surya.
Dari perdebatan yang berlangsung, Ki Tedjo tetap dengan sikapnya. Dia lalu mengamini permintaan sepasang suami istri miskin yang menginginkan pementasan wayang untuk meruwat anak mereka. Dalam pementasan ruwat itu, Ki Tedjo melakoni peran sebagai Karna Tanding.

Mendengar itu, sontak anak buah Ki Tedjo terkejut. Karena, lakon Karna Tanding menceritakan peperangan, tidak pas dilakoni untuk ruwatan. Mendengar komplain itu, Ki Tedjo menjawab, “Sudah saatnya dalang tidak mendengarkan pakem, tapi dalang harus mendengarkan suara rakyat." Lalu, Ki Tedjo berupaya mengalihkan topik pembicaraan. Dia menanyakan siapa di antara anggotanya yang ingin memerankan Arjuna.
Beberapa anak buahnya sepakat, jika Akbar yang pantas melakoni peran Arjuna, anak Ki Tedjo. Mendengar hal itu, Cak Lontong protes. Dia tidak terima Akbar menjadi Arjuna. Namun, protes itu tenggelam oleh suara anggota lain yang bulat memilih Akbar. Akhirnya, Ki Tedjo menasihati keduanya agar saling berdampingan dan tidak saling berlawanan.
Penghormatan pada Ki Nartosabdo
Penggalan kisah tersebut merupakan bagian dari cerita pementasan ke-22 Indonesia Kita yang bertajuk Sabdo Pandito Rakjat. Pementasan yang disutradarai Sudjiwo Tedjo itu ditujukan sebagai bentuk penghormatan kepada salah satu tokoh dalang dan budayawan Jawa, Ki Nartosabdo.

Lelaki yang lahir di Klaten, Jawa Tengah, 25 Agustus 1925 itu dikenal sebagai seniman sejati. Beberapa karya ditelurkannya, baik berbentuk seni pedalangan maupun lagu-lagu berbahasa Jawa. Salah satu karya seniman yang wafat pada 7 Oktober 1985 itu yang sangat dikenal oleh seluruh etnis Jawa ialah lagu Prahu Layar. Lalu itu juga dikenal orang non Jawa yang tinggal di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bisa dikatakan, lagu itu seperti lagu kebangsaan orang Jawa. Ki Narto juga dikenal sebagai pencipta lagu Gambang Suling dan Ibu Pertiwi.
Dalam pementasan Sabdo Pandito Rakjat, beberapa karya Ki Narto disuguhkan. Beberapa lagu ciptaannya dikemas secara kreatif oleh Bintang Irdianto, selaku penata musik pementasan tersebut. Kreasi itu mampu memunculkan dimensi imaji tersendiri yang menyuarakan makna-makna yang tersirat dari cerita pementasannya.
Pementasan tersebut juga memadukan berbagai unsur kesenian, dibalut dengan teknologi. Hal itu terlihat dari penggunaan layar multimedia untuk menampilkan penggalan kisah wayang di tengah-tengah cerita.

Lalu, tarian-tarian tradisional dan modern yang ditampilkan, saling mengisi satu dengan lainnya. Apalagi, pada pementasan kali ini, turut serta Didik Nini Thowok, maestro tari, yang mempertontonkan kemahirannya dalam menari berbagai tarian tradisional Jawa.
Pesan dan Kritik terhadap Realitas
Pementasan Sabdo Pandhito Rakjat menebar pesan berbalut kritik terkait keadaan sosial, politik, dan budaya Indonesia akhir-akhir ini. Misalnya, tentang perseteruan antarwarga yang di berbagai media, khususnya media sosial. Hal itu terlihat dari peran yang dilakoni Cak Lontong dan Akbar yang diperankan Insan Nur Akbar yang saling berseberangan. Menariknya, Lontong menggunakan kemeja putih, sedangkan Akbar berkemeja kotak-kotak.
Tanda dalam kostum yang dikenakan Lontong dan Akbar itu memiliki kaitan makna dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Kala itu, Prabowo Subianto sebagai calon presiden menggunakan kemeja putih sebagai ciri khasnya dan Joko Widodo menggunakan kemeja kotak-kotak.
Kala itu, antarpendukung calon presiden saling mencerca dan saling menghina di berbagai medium. Kondisi itu terus berlanjut hingga saat ini. Kini, yang terjadi antara pendukung pro Presiden Jokowi dengan yang kontra.

Secara tak langsung, pertarungan antara pendukung dan yang kontra itu diibaratkan seperti pertarungan Karna dan Arjuna dalam lakon Karna Tandhing. Keduanya itu merupakan sosok yang saling bermusuhan, meski mereka tahu dan sadar bahwa mereka berdua adalah saudara se-ibu.
Peran itu merepresentasikan kondisi saat ini. Suhu politik di tingkat elit, turut merenggangkan hubungan di tingkat bawah, khususnya para pendukung di masing-masing kubu. Jika sentimen antar kelompok itu dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan menjadi bom waktu yang bisa merusak harmoni sosial yang sudah sekian lama mewujud dalam bingkai keanekaragaman. Sungguh miris ketika melihat pesan-pesan kebencian dan ego kelompok di media sosial. Masing-masing pihak saling menghina, mencerca, dan merasa paling benar. Perseteruan di dunia maya itu dikhawatirkan akan membawa petaka dalam kehidupan sosial di kemudian hari.
Kritik juga nampak pada adegan Pak Surya yang diperankan Marwoto, yang membagi-bagikan uang. Peran itu merupakan representasi perilaku politik para elit yang gemar menebar uang dengan tujuan kekuasaan. Dengan berkekuatan uang, Pak Surya mampu mempengaruhi para anggota kelompok seni Ki Sabdo Tedjo (Sudjiwo Tedjo) agar melawan pemimpinnya. Peran yang dilakoni Pak Surya itu juga merepresentasikan perilaku sebagian masyarakat Indonesia saat ini yang demi mengamankan kepentingannya, harus menebar suap kepada pihak lain lain. Budaya suap itu yang kemudian menyuburkan praktik korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa ini.
Bagaimana dengan sosok Bu Kunti yang diperankan Happy Salma, istri Ki Tedjo? Perempuan itu menjadi simbol ibu pertiwi. Dalam adegan yang menyinggung Lontong dan Akbar, Bu Kunti selalu bersedih dan menangis. Sebab, dua anak kandungnya yang beda suami itu tak pernah henti berseteru. Lontong merupakan anak dari hasil pernikahannya dengan Pak Surya.
Sementara Akbar dari pernikahannya dengan Ki Tedjo. Ekspresi kesedihan Bu Kunti itu merepresentasikan perasaan bangsa ini saat ini, di mana sesama anak bangsa masih saja berseteru. Dan, ironisnya, perseteruan terjadi hanya karena masalah sepele, seperti halnya Lontong dan Akbar yang memperebutkan siapa yang lebih pantas memainkan peran sebagai Arjuna.

Pementasan kali ini juga kental dengan kritik dan pesan-pesan terhadap seni. Misalnya, saat dialog antara Ki Tedja dengan anggota kelompok seninya. Pernyataan Ki Tedja mengingatkan pentingnya idealisme dalam diri seorang seniman. Dia menegaskan, seniman bukan artis yang karya-karyanya didedikasikan untuk mendapatkan keuntungan materi. Sementara seniman, melahirkan karya berdasarkan suara hati nuraninya, meski kadang tak sejalan dengan kondisi keuangannya saat ini.
Lalu, kritik lainnya terlihat saat adegan Ki Tedja yang tengah melatih tari kepada Gina yang diperankan Gina Sinaga. Ketika latihan, Gina mengeluhkan cara Ki Tedja menari. Protesnya itu memancing kegeraman Ki Tedja. Saat marah, Ki Tedja mengatakan, untuk menjadi penari harus melalui proses yang butuh waktu tak sebentar.
Kritik itu mengacu pada kondisi seni dan hiburan di tanah air saat ini, yang proses kreasinya berlangsung instan. Adegan itu juga menjadi lahan kritik bagi generasi muda saat ini. Di era generasi Z saat ini, anak muda sering enggan melalui suatu proses dalam berkarya. Mereka cenderung instan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Cara-cara itu yang yang kemudian mereduksi kualitas karya seni. Wajar jika khalayak sudah tidak lagi menghargai kualitas seorang seniman. Apresiasi lebih pada tampilan fisik, meski tidak memiliki kualitas yang baik.
Adegan latihan tari itu juga mengandung pesan pentingnya menghargai perbedaan dalam kehidupan. Pesan itu nampak ketika Didik Nini Thowok memeragakan beberapa ciri perbedaan tarian Jawa. Perbedaan itu mampu menunjukkan keindahan dalam suatu kesatuan bangsa dan budaya.
Perbedaan adalah realitas sosial yang jika dikelola dengan baik, maka kian mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Secara umum, Sabdo Pandito Rakjat juga menebar pesan agar bangsa ini kembali bangkit dari keterpurukan. Dalam konteks ini, pentingnya suara rakyat didengar dan menjadi acuan para pemimpin bangsa ini.

Meski terdapat kritik tajam dan pesan mendalam, pementasan Sabdo Pandito Rakjat, tetap dibalut humor menggelitik. Kehadiran Inayah Wulandari Wahid, putri bungsu Presiden Ke-4 Abdurahman Wahid, menjadi bumbu humor tersendiri. Sebab, Inayah berperan sebagai seorang tukang jamu yang polos, namun vokal. Dia seakan menjadi salah satu corong rakyat dalam memaknai kondisi yang dihadapi bangsa saat ini.
Memang, suara-suara arus bawah perlu didengar karena merekalah yang merasakan secara langsung kehidupan saat ini. Meski pandangannya sederhana, namun merepresentasikan realitas. Bukan seperti lelaku sebagian abdi negara yang cenderung mengada-ada dengan tujuan asal bapak senang (ABS).
Humor-humor menggelitik pun sangat kental dihadirkan oleh Trio GAM (Guyonan Ala Mataraman). Di pementasan itu, Gareng, Wisben, dan Joned, berhasil memancing tawa menonton dengan banyolan-banyolan sederhananya, yang juga kental dengan kritik. Sebagai pementasan Indonesia Kita terakhir di tahun 2016, Sabdo Pandito Rakjat, mampu menghibur, sekaligus mengajarkan khalayak dan pemerintah dalam menyikapi kondisi yang dihadapi bangsa ini.
Muhammad Khairil