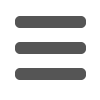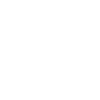Perempuan di Tanggal Dua Puluh Enam

26 Pebruari 1987
Mata ini sudah mulai lelah. Maklum saja waktu sudah menunjukan pukul 02.00 dinihari. Saya masih menulis surat untuk seseorang yang namanya sudah berlabuh di hati.
Kata-kata yang dirangkai penuh prosa dengan idiom-idiom mirip tulisan Leila S Chudori, wartawati majalah Tempo yang begitu menyihir setiap jengkal kata demi kata. Saat itu saya baru duduk di kelas dua es-em-pe, kesusasteraan melalui tulisan Leila S Chudori begitu menjadi hidup dan mengispirasi.
Penaku terus menulis kata dengan muatan cinta, persudaraan dan persamaan tergores pada lembaran kertas berwarna ping dengan lambang zodiak pisces di sebelah kanan. Ini ungkapan yang sangat istimewa di saat sang pujaan hati tengah berulang tahun.
Silvia Kusmarini hanya tersenyum dan dua kata yang terlontar “ terima kasih, “ saat menerima surat yang kuberikan dengan harap-harap cemas. Sebelum meninggalkan Silvia, begitu dia biasa disapa, saya menjabat tangannya sambil mengucapkan ”selamat ulang tahun, semoga panjang umur.“ Saya memperhatikan reaksinya hanya tersenyum tanpa kata-kata.
Esok harinya Silvia membalas surat yang saya tulis. Berbunga sekali rasanya. Saya mulai menduga, menafsirkan eksotisme dalam pikiran yang penuh duga, menjauhkan praduga yang menyesakkan dada kalau-kalau balasannya menjauhkan harapan-harapan.
Saya mulai membacanya ;
“ Hidup adalah cinta “
Salam,
Silvia Kusmarini
26 Juni 1995
Tanpa membuang waktu saya dan beberapa aktivis perempuan bergegas menuju Purbalingga, tepatnya di desa Grecol. Perjalanan malam yang penuh dukacita menyisakan cerita getir. Mbok Inah, salah seorang survivor Jugun Ianfu yang telah tutup usia, adalah saksi sejarah kelam perang dunia ke II atas kesemena-menaan kaum serdadu negara matahari terbit.
Mata saya menatap kosong ke depan dengan sesekali menggigit ujung kuku sambil mengingat cerita Mbok Inah, perempuan yang pernah menjadi pegawai rendahan NIS ( Nederlandsch Indishe Spoorweg Naatschappij ), sebuah perusahaan perkereta apian di Semarang.
Mbok Inah memang hanya enam bulan bekerja di NIS, dia dikeluarkan akibat ikut aksi pemogokan buruh massal yang berdampak pada stagnasi lumbung ekonomi kaum imperialis.
Masa perang dunia ke II mengantarkan Mbok Inah menginjakkan kakinya di Kalimantan, bukan sebagai pekerja pelayan restoran, tetapi sebagai pemuas nafsu serdadu Jepang.
Mbok Inah harus melayani kebutuhan biologis kaum lelaki yang di negeri asalnya di eluk-elukan sebagai ksatria. Mbok Inah melayani secara paksa, diperkosa, sepanjang hari, penuh kekerasan seksual. Sampai-sampai rahimnya rusak. Harapan keberlangsungan hidup dengan keluarga bersuami dan anak, lantak sudah. Kalaupun masih tersisa, hanyalah impian. Serdadu Jepang telah menguburkan segalanya bagi mbok Inah. Jugun Ianfu itulah stempel yang melekat pada diri Mbok Inah.
Kini mbok Inah telah wafat. Kehormatan dan harga dirinya belum pernah dikembalikan, pemerintah sampai saat ini tidak pernah memperhatikan eks jugun ianfu, boro-boro mau memberi pengakuannya sebagai pahlawan memperhatikan eks jugun ianfu yang telah uzur pun telah terhapus dalam lembar-lembar kepentingan kekuasaan untuk dirinya, untuk kelompoknya, untuk partainya, untuk koleganya, untuk negara sahabat yang telah memberikan bantuan dan utang.
Sesampai di Grecol saya memberikan penghormatan terakhir kepada Mbok Inah, seraya memanjatkan doa di hadapan tubuh senja yang terbujur lelah… Semoga Tuhan menempatkan di sisi makhluk yang mulia.
Masih teringat kata-kata Mbok Inah saat mengakhiri kisah pahit getirnya bahwa hidup bukanlah penyesalan, tapi hidup adalah berbagi antara mbok dan sesama serta semesta alam, itulah persembahan yang mbok bawa pulang tuturnya.
26 Agustus 2002
Sebuah pesan singkat mampir di hp saya. “Mas Tian kiranya dapat menghubungi aq di nomor ini, pls ( Rere / Theresia Widyastuti ).” Saya menghubunginya melalui telepon seluler, suaranya terdengar tertahan dan terbata-bata, suara dari seoorang yang sedang lelah dan sakit. Rere mengharapkan saya mengunjunginya.
Apa gerangan yang menimpa Rere? Aku mulai bertanya-tanya dalam hati. Bukankah Rere yang aku kenal penuh pesona dan glamour. Perempuan cantik dengan postur tubuh ideal, lelaki mana yang tidak menelan ludah ketika melihat sosok Rere seorang model papan atas yang selalumenghiasi lenggak-lenggok catwalk dalam sesi fashion show dari para perancang busana ternama.
Saya memenuhi undangan untuk menemui Rere, sesuai alamat yang ia berikan. Saya mulai menduga bahwa Rere tengah menderita. Saya tersentak, karena alamat yang dia berikan hanyalah rumah di perkampungan slum.
Tadinya saya tidak percaya rumah yang terbilang kumuh itu adalah tempat tinggal Rere, karena sepengetahuan saya Rere tinggal di hunian cluster berarsitektur eropa. Memiliki halaman yang luas dengan tanaman rimbun dan etalase mobil mewah berjejer lima.
Kini saya memasuki ruangan yang sesak dan pengap. Rere terbaring lemah. Bibirnya mulai bergetar menceritakan nasibnya. Dia ungkapkan keluh kesahnya, menceritakan suaminya telah berpaling ke perempuan lain, menceritakan kanker serviks yang terus menggrogoti leher rahimya.
Kini Rere dalam kesendirian, suaminya telah pergi, di saat Rere tidak dapat menunaikan kewajiban biologisnya kepada suami. Frans, suami Rere yang telah menghisap nikmat madu yang tersedia pada lekuk tubuh Rere.
Kini Frans telah menghilangkan Rere dalam intuisi naluri kelelakiannya. Rere kini penuh aroma bau yang menyengat human papilloma, virus yang mengubah Rere manjadi makhluk paling sial.
Air mata Rere terus meleleh melewati pipinya yang sudah mulai keriput.
“Mas ajari aku berdoa agar bisa bertemu Tuhan”, Rere memelas mengharapkan saya untuk bisa menyejukkan hatinya.
“Saya Muslim, Re. Saya akan berdoa sesuai keyakinan saya untuk kamu.“ “Aku malu dan takut kepada Yesus, Mas…saat aku di atas, aku melupakan Yesus,” kata Rere dengan penuh penyesalan.
Ketika saya berikan pengertian kepada Rere, akhirnya Rere setuju untuk saya ajak menemui romo di salah satu gereja katolik yang tidak jauh dari tempat tinggal Rere.
Romo dengan sabar menuntun Rere untuk ‘bercengkerama’ dengan Yesus. Human Pappiloma Virus telah mempertemukan kerinduan seorang Rere dengan Yesus, yang dia yakini sebagai juru selamat, yang menebarkan cinta dan kasih.
“Mas, terima kasih ya? Aku telah menemukan-Nya. Sekarang, aku tak bergantung kepada Frans, ketergantungan sesungguhnya pengelabuan ketidakberdayaan,“ kata Rere, sambil melanjutkan pembicaraan, “tidak lama lagi aku akan pulang bersama virus pappilloma, hidup itu mesti terima kasih.“
(Cerpen ini dipersembahkan untuk sahabat terkasih Selfia Primandari yang telah berpulang tanggal 10 Maret 2018)