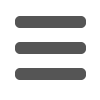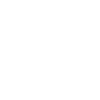Gerakan Jempol Pemirsa Mengkritisi Talkshow Televisi

Catatan N. Syamsuddin Ch. Haesy
PROGRAMA siaran talkshow televisi Indonesia, berubah sejak terjadi perubahan besar tahun 1999, menyusul kebijakan pemerintah BJ Habibie, melalui Keputusan Menteri Penerangan Junus Josfiah terkait dengan kebebasan pers.
Sejak saat itu, kita mempunyai tiga peraturan perundang-undangan yang meski terkait satu dengan lainnya, namun berdiri sendiri-sendiri. Yaitu, Undang Undang Pers, Undang Undang Perfilman, dan Undang-Undang Penyiaran.
Tiga perangkat hukum itu, tak sertamerta bisa menjangkau percepatan perubahan dunia komunikasi (termasuk komunikasi sosial, politik, dan komunikasi massa). Terutama sejak 2014, ketika media massa, khasnya televisi dan media arus utama (media mainstream) tak lagi murni independen terhadap pemerintah, dan menunjukkan keberpihakan untuk menjaga tokoh kemasannya (Presiden Joko Widodo) sebagai media darling.
Situasi ini membuat arus informasi media sangat crowded, apalagi ditingkah dengan penggalangan besar konten media sosial yang tak terkontrol, oleh para cyber trooper (termasuk akun pembiakan) yang banyak memproduksi informasi wadul (hoax) dengan muatan kepentingan politik sesat dan rendahan.
Sebagian terbesar acara talkshow televisi berubah menjadi ajang silang sengketa wacana yang tak jelas juntrungan, namun jelas arahnya : mempertahankan proses pencitraan satu tokoh kemasan, dengan mengabaikan ruang kontestasi citra, melalui proses image engineering yang paling elementer.

Kepentingan masyarakat, selaku pemirsa untuk memperoleh informasi cover both side, balance, dan obyektif tak terpenuhi. Terutama karena framing media yang kuat sejak programa siaran televisi dirancang.
Hanya ada satu dua programa siaran talkshow televisi yang masih memberi ruang adil kepada pemirsa untuk mendulang informasi yang seimbang, seperti Indonesia Lawyers Club (ILC) – TVOne yang dipandu jurnalis senior Karni Ilyas.
Meski tak terhindar menghadirkan figur yang belum layak dan belum patut sebagai narasumber, dalam banyak hal, ILC – TVOne mampu menjadi katarsis di tengah simpangsiur arus informasi wadul yang tak sehat untuk bangsa ini.
Selain itu, masih ada talkshow televisi Kick Andy, dengan format lain, yang memberi ruang bagi pemirsa untuk mendapat psychofastfood yang lumayan, ‘membasahi’ dimensi kemanusiaan kita.
Selebihnya? Kita hanya beroleh sajian talkshow televisi yang hanya mempertontonkan sentak-sengor (perdebatan tanpa substansi dengan nada suara dan emosi tinggi). Lantas, pemirsa mendapatkan sajian talkshow televisi yang cenderung merupakan medium ekspresi host-nya yang gamang oleh sindroma eksistensialismus. (Baca juga : Pelajaran dari Amanpour Ihwal Host Talkshow Televisi)

Dari pendekatan analisis semi diskursif terinspirasi (Charaudeau, 1997), rata-rata talkshow yang didominasi oleh konten politik, masih menghadirkan pembelahan intra generik, dan para narasumber (terutama yang menjadi representasi) kekuatan politik (baik formal kelembagaan) dan politik ekspressi masih sibuk menggunakan acara talkshow itu sebagai medium pencitraan. Terutama, karena host atau pemandu acara talkshow itu, tak membebaskan diri (terutama fikirannya) dari dependensi atau ketidak-merdekaan dari pengaruh politik.
Meminjam pandangan Joëlle Desterbecq (2011) dengan analisis semio-diskursif, kita melihat, sebagian terbesar programa siaran talkshow di televisi Indonesia kini, merupakan "produk jadi", dengan mempertimbangkan interest “ruang internal” kelembagaan medianya. Artinya, programa siaran talkshow televisi itu, sangat bergantung pada kebijakan manajemen institusi dan amat bergantung kepada siapa pemiliknya, dan orientasi politik pemiliknya.
Akibatnya, seperti pandangan Charaudeau (1997), programa siaran talkshow televisi kita, masih didominasi oleh sistem verbal dan belum bergeser ke sistem semiologis lainnya yang lebih kaya dan beragam sikapnya dalam melihat fenomena dan peristiwa mutakhir yang berkembang di masyarakat.
Hasilnya? Programa siaran talkshow televisi, lebih berkutat pada bagaimana merekonstruksi wacana dari beragam kalangan kepentingan politik yang tak proporsional dan tak sebanding. Konten yang disajikan dalam bentuk topik, secara intra generasional, belum mampu memisahkan (bahkan memilah) antara kepentingan pemirsa secara universal dengan kepentingan kelembagaan (juga kepemilikan) televisi yang menayangkan program tersebut.
Situasi ini pernah dialami oleh lembaga pertelevisian di Belgia dalam memilih format universal, karena masih terjebak pada persoalan “ruang internal” antara pemikiran yang dipengaruhi oleh kultur Belanda dan kultur Perancis. Situasi ini, mewarnai kegamangan talkshow programme producer di lanskap pertelevisian Eropa Barat, yang didominasi oleh pemikiran kelembagaan partai atau lembaga politik praktis, sekaligus mengabaikan realitas arus besar orientasi politik para media mogul yang menguasai bisnis pertelevisian.

Perubahan format dan formula programa siaran talkshow televisi Eropa Barat, mengalami perubahan kongkret, ketika Aurélien Le Foulgoc telah menyoroti pembalikan kurva pertelevisian Perancis yang terjadi antara 1990 dan 2002. Khasnya, antara jumlah program politik dan hiburan (termasuk programa siaran talkshow, yang menjadi tuan rumah arus pemikiran lembaga politik).
Le Foulgoc (2003), menyebut, program talkshow sejak tahun 2000 telah didominasi oleh arus pemikiran dan wacana politik, kendati programa siaran itu tidak didedikasikan untuk politik.
Sejumlah penelitian – terutama dengan menggunakan content analysis – menemukan fakta, bagaimana pertelevisian di Belgia, di awal abad ke 21 itu, tidak mempunyai sistem pengarsipan produksi talkshow televisi, sehingga kerap terjadi daur ulang isu-isu politik yang menempatkan pemirsa sebagai obyek pasif penyiaran.
Programa siaran talkshow televisi, kemudian menjadi medium bagi kalangan praktisi dan petinggi politik (terutama yang berkuasa) melakukan upaya penetratif hypodermic untuk ‘merampas’ hak pemirsa, mendapatkan informasi yang jernih dan jelas tentang berbagai peristiwa politik yang terjadi. Tak terkecuali gamangnya pemerintahan ketika menghadapi krisis global.
Penelitian Observatoire du récit média (unit penelitian dalam analisis media di Universitas Louvain) dalam penelitiannya (2005-2006) menemukan realitas, tatakelola programa siaran talkshow televisi (khasnya di Belgia) sangat intuitif.
Produser, desainer, sampai host programa talkshow menempatkan dirinya hanya sebagai ‘pelayan’ kepentingan politik, mengikuti kondisi yang berlaku di masing-masing lembaga penyiaran televisi.

Ketika Ted Turner mengubah sistem produksi penyiaran berita dan informasi yang lebih efisien di CNN, dan menyajikan beberapa program talkshow yang lebih adil dan proporsional, sekaligus menjaga newsroom dari kepentingan petinggi dan lembaga politik, baru mereka berubah secara evolutif.
Tetapi, secara praktis, kepentingan pragmatisme politik masih mendominasi manajemen pertelevisian di Eropa Barat. Antara lain dengan memberikan karpet merah kepada lembaga politik praktis (partai politik) dan para anggota parlemen untuk masuk ke dalam sistem, bahkan sampai cawe-cawe dalam memilih topik konten.
Para brodkaster dan jurnalis televisi yang masih bertahan dengan idelisme, mesti menggerakkan profesionalisme-nya untuk terus memelihara nilai inti profesi jurnalis : berbicara kebenaran secara adil, manusiawi, dan fair. Sekaligus mempertahankan newsroom dari campur tangan lembaga politik yang masuk melalui pemilik stasiun televisi.
Tujuannya jelas: terciptanya kondisi manajemen program, produksi, dan penyiaran talkshow televisi yang independen.
Kendati demikian, temuan Maingueneau (1998), terkait pemanfaatan talkshow untuk memelihara citra publik penguasa dan partai politik, dan reduksi citra positif lawan politiknya, tak juga terbantahkan.

Dalam situasi ini, para jurnalis televisi dan produser terus berjuang mempertahankan energi kreatif mereka, dengan memasukkan anasir psikologi penyiaran dalam memilih format dan host (pemandu) talkshow.
Hal itu dilakukan untuk terus membersihkan saluran televisi yang menjadikan talkshow sebagai sajian programa utama, dari kontaminasi pragmatisme politik yang gencar merasuki genre programa siaran di tengah kompetisi antar saluran siaran televisi.
Semua itu terjadi, bersamaan dengan munculnya kesadaran untuk tidak mudah ‘meminjamkan’ jaringan perseptual kepada lembaga (termasuk partai) politik, dan orang-orang (tak terkecuali akademisi) yang sudah terkontaminasi oleh kepentingan politik (dan komersial) sesaat.
Akankah pertelevisian Indonesia mampu menghormati pemirsanya, dengan memproduksi dan menyiarkan programa siaran talkshow yang sehat bagi kepentingan transformasi masyarakat (khalayak, pemirsa), sebagai kontribusi terhadap kemajuan bangsanya? Tak mudah menjawab pertanyaan ini.
Yang pasti, perlu gerakan massif memelihara kesadaran kolektif masyarakat – melalui community education -- untuk mau dan mampu menggunakan jempolnya, memindahkan saluran, ketika suatu stasiun televisi hanya menyajikan talkshow yang terasa terkontaminasi kepentingan politik sesaat. |
Bandung, 28/1/18
Rangkaian Artikel Menyambut Hari Pers Nasional 2018