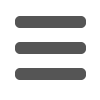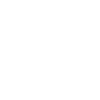Mengenang Kudatuli, Kala Oposisi Digembosi

AKARPADINEWS.COM| Kisruh yang dialami Partai Golkar yang oleh kubu Aburizal Bakrie disebabkan karena intervensi pemerintah, mengingatkan Yusril Ihza Mahendra akan peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli). Peristiwa kelabu itu menimpa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.
Kala itu, PDI mengalami tekanan politik luar biasa dari rezim Orde Baru (Orba). Rezim penguasa yang ditopang kekuatan politik Golkar dan militer, tidak ingin PDI kubu Megawati tumbuh besar menjadi pesaing politiknya. Berbagai cara dilakukan untuk memecah belah partai berpaham nasionalis itu.
"PDI Perjuangan pernah mengalami betapa sakitnya diadu domba oleh pemerintah yang mendukung kubu Soerjadi melawan kubu Megawati. Apa yang pernah di masa lalu itu jangan diulangi lagi saat PDIP menjadi partai penguasa (saat ini)," kata Yusril yang juga kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal di Jakarta, Kamis (12/3).
Megawati tentu ingat betul peristiwa berdarah itu. Kudatuli merupakan peristiwa yang menunjukan arogansi penguasa Orba terhadap lawan-lawan politiknya. Demi mempertahankan kekuasaan, rezim Orba memukul semua lawan-lawan politiknya. Politik pecah belah pun dilakukan. Penguasa hanya ingin partai politik dikendali oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaannya.
Kala itu, popularitas Megawati tengah moncer. Megawati yang dianggap membahayakan kekuasaan Orba, lalu diadu oleh sesama rekannya yang ingin berebut kuasa di PDI. Kala itu, yang menjadi boneka Orba untuk melawan Megawati adalah Soerjadi.
Rezim Orba alergi terhadap Megawati yang dalam Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya 1993, menang secara aklamasi. Dia dipercaya kader dan simpatisan menjadi Ketua Umum PDI. Namun, lantaran tidak direstui penguasa, kekuasaan Megawati di PDI diutak-atik.
Rezim Orba mensponsori Kongres PDI di Medan, Sumatera Utara tahun 1996. Kongres itu menjadikan Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Namun, Megawati beserta pendukungnya menolak.
Pada tanggal 27 Juli 1996, pendukung Soerjadi melakukan upaya paksa, merebut kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia ( DPP PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang dikuasai Megawati. Kerusuhan pun sulit dihindari dan meluas.
Amuk massa membakar kendaraan dan beberapa gedung. Rezim penguasa lalu menuduh aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai penggerak kerusuhan. Budiman Sudjatmiko, pentolan PRD diciduk dan divonis hukuman 13 tahun penjara. Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut lima orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136 orang ditahan.

Di bawah kendali Soerjadi, PDI makin ambruk di Pemilu 1997. Kadernya banyak yang hijrah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga memunculkan koalisi ideologis yang menjadi penyeimbang kekuatan Orba yang dikenal dengan sebutan "Mega Bintang".
Begitulah dinamika politik di era Orba. Demokrasi mati suri. Meski pelaksanaan Pemilu kala itu dapat berlangsung secara periodik (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997), suksesi didesain sedemikian rupa untuk mengukuhkan kekuasaan Orba.
Untuk mempertahankan hegemoninya, penguasa Orba menerapkan peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975 sehingga Pemilu hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya (Golkar). Pemilu yang direkayasa menjadikan Golkar sebagai alat politik Orba selalu tampil menjadi pemenang.
Peran militer dalam politik juga sangat besar. Keterlibatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)—yang sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam politik, dikukuhkan lewat konsep Dwifungsi ABRI.
Setelah Orde Baru tumbang, era reformasi menghembuskan angin segar bagi kehidupan berdemokrasi. Partai politik tumbuh bak jamur di musim hujan, menjadi lebih mandiri dan independen. Politisi berebut dukungan rakyat agar dapat menduduki pucuk kekuasaan.
Dan, PDI--yang kemudian bermetamorfosis menjadi PDI Perjuangan, yang tadinya tak pernah merasakan nikmat kekuasaan, menjadi partai pemenang saat Pemilu tahun 1999. Partai besutan Megawati itu menggusur 48 partai politik peserta Pemilu, termasuk Golkar yang ditopang infrastruktur dan logistik yang kuat.
Sayang, Megawati kala itu tak berhasil menjadi Presiden karena dihadang koalisi lintas partai di parlemen. Maka, munculah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang didukung koalisi poros tengah yang diinisiasi Amien Rais.
Meski suara PDIP paling dominan, Megawati hanya menjadi wakil presiden. Baru pada tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur diturunkan dari kursi kekuasaan setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Megawati pun dilantik menjadi Presiden RI ke-5.
Kini, PDIP kembali memegang tampuk kekuasaan setelah 10 tahun menjadi oposisi. Partai berlambang benteng bermoncong putih itu juga berhasil menempatkan kadernya, Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Jokowi mencapai puncak kekuasaan tertinggi di negara ini setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2014 lalu. Dia mengalahkan Prabowo Subianto, calon presiden yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya.

Rakyat tentu mengharap, kepemimpinan Jokowi dapat mengukuhkan demokrasi yang sudah berjalan dengan baik, harmoni, dan mensejahterakan rakyat. Namun, realitas politik menunjukan, ada kecenderungan demokrasi terdistorsi lantaran elit politik terjebak dalam pertarungan politik yang tiada akhir.
Buktinya, sejak berakhirnya Pilpres 2014, konstelasi politik nasional masih saja panas. Elit politik terbelah. Setelah kalah di Pilpres, kubu Prabowo membentuk Koalisi Merah Putih (KMP) dan berhasil mempecundangi kubu Jokowi, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen.
KMP menyapu bersih jabatan strategis di DPR dan pimpinan MPR. Dominasi (Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP), ditambah dengan Demokrat di parlemen, membuat KIH khawatir tak mampu membendung manuver politik KMP yang dapat menghambat kinerja pemerintah. Melihat manuver tersebut, rezim penguasa pun mengatur celah untuk memperlemah kubu penyeimbang.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly boleh saja membantah jika pemerintah mengintervensi urusan internal Golkar dan PPP. Namun, ada kesan kuat jika menteri yang merupakan politisi PDIP itu menggunakan kekuasaannya untuk menarik dua partai itu ke kubu pendukung pemerintah.
Keputusan Yasonna mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono, tentu mematik amarah kubu Aburizal Bakrie. Keputusan Menkumham itu dianggap beraroma politis.
Yasonna dituding memanfaatkan konflik di internal Golkar dengan cara memihak kubu Agung lantaran ingin Golkar merapat ke pemerintah. Manuver politik Menkumham itu dibalas dengan langkah hukum dan politik. Selain melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kubu Ical juga mengancam akan menggulirkan hak angket DPR. Keputusan
Menkumham itu membuat beringin semakin goyang. Sampai-sampai, kedua kubu saling gontok-gontokan. Dan, bukan mustahil, konflik itu merambah ke kader Golkar di daerah-daerah. Jika kondisinya demikian, maka yang diuntungkan adalah partai lain.
Mereka yang sakit hati, kemungkinan hijrah ke partai lain. Atau, bisa juga kubu Aburizal Bakrie membuat partai baru, seperti yang dilakukan Surya Paloh dengan mendirikan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), setelah kalah dari Aburizal dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar.
Sementara kubu Agung mengingatkan para pendukung Ical agar mengikhlaskan mandat kepada Agung untuk memimpin Golkar. Kubu Agung juga bergerak cepat untuk menjalin komunikasi politik dengan partai lain. Agung menyambangi sejumlah pentolan partai yang tergabung di KIH, seperti Surya Paloh (Nasdem), Megawati (PDIP), Sutiyoso (PKPI), dan Wiranto (Hanura). Dia juga menyambangi pentolan partai dari kubu KMP seperti Zulkifli Hasan (PAN).

Sulit dibantah jika pemerintah mengklaim tidak cawe-cawe dalam urusan Golkar. Pasalnya, bagi pemerintah, dukungan politik Golkar sangat diharapkan. Dengan mengesahkan kubu Agung, pemerintah mendapatkan dukungan politik yang kuat di parlemen. Agung sebelumnya telah berkali-kali menyatakan sikapnya mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
Upaya melemahkan KMP juga terlihat saat Yasonna melakukan langkah serupa dengan mengesahkan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) kubu Muhammad Romahurmuziy yang cenderung mendukung pemerintah.
Sementara PPP yang dipimpin Djan Faridz yang didukung Suryadharma Ali, memilih merapat ke KMP. Putusan Menkumham pun diperkarakan kubu Suryadharma ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. Hingga akhirnya, majelis hakim membatalkan SK Menkumham tersebut. Namun, Menkumham bergeming. Yasonna ngotot kepengurusan DPP PPP kubu Romahurmuziy yang sah. Sampai-sampai, dia mengajukan banding.
Jika campur tangan pemerintah tersebut terus dilakukan, maka tak ada bedanya dengan cara rezim otoriter Orba saat memecah belah PDI dalam peristiwa Kudatuli.
M. Yamin Panca Setia/Ade Setyawan