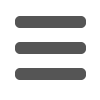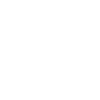Dramaturgi di Panggung Suksesi

AKSENTUASI kala berbicara begitu tertata. Terdengar pula menyakinkan di telinga. Penampilannya pun dipoles sedemikian rupa. Kadang mereka tampil rada agamis. Kadang juga berpenampilan stylish dan modernis. Bisa pula mereka hadir dengan corak tradisionalis. Tergantung dengan siapa berbicara dan di mana mereka berada.
Mereka juga mendadak menjadi pemurah. Mensponsori berbagai kegiatan, disertai suguhan hiburan yang menghadirkan artis ibukota dan undian berhadiah. Ada pula di antara mereka yang menebar sembako kepada warga.
Itulah kesan yang nampak di panggung suksesi. Simak saja perilaku mereka yang berlaga di ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Mereka begitu gencar menebar pesona. Bahkan, sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dibuka, mereka sudah pasang kuda-kuda. Mereka juga menyusup ke ruang-ruang publik lewat poster, baliho, stiker, dan spanduk. Termasuk, jor-joran mempromosikan diri dengan memasang iklan di media massa.
Namun, begitu kuat kesan dramaturginya. Lewat isyarat verbal dan non verbal yang diperlihatkan, mereka ingin dikesankan sebagai pemimpin yang dekat dan melayani. Publik yang menggunakan rasionalitasnya dapat menilai makna yang tersirat dari aksi yang dilakoni mereka. Tak lain, karena mereka ingin mendongkrak citra agar dapat memenangkan laga Pilkada.
Tak salah jika mereka melakoni dramaturgi. Toh, tak hanya politisi. Setiap manusia dengan berbagai latar belakang juga melakoni dramaturgi. Sosiolog Erving Goffman (1959) yang menggulirkan teori dramaturgi menjelaskan, perilaku manusia itu laksana berada di panggung sandiwara. Sebagai aktor di atas panggung, Goffman menjelaskan, perilaku manusia dapat berubah-ubah, tergantung kepentingan dan dengan siapa dirinya berinteraksi.
Di panggung front stage (ranah publik), individu melakoni peran sesuai skenario. Dia dituntut berperan dengan baik agar menimbulkan kesan positif dari orang lain yang menyimaknya. Sementara di panggung back stage (ranah privat) yang tanpa penonton, manusia bebas melakoni karakter dan perilaku sebenarnya, tanpa terikat skenario.
Agar sukses mementaskan peran (performance), tentu perlu ada persiapan. Mereka harus memahami skenario, menguasai panggung, dan piawai berinteraksi dengan audience. Nah, di pangung suksesi (front stage), itu dilakukan politisi dengan memoles penampilan, mengatur sikap, dan menata tutur kata. Bila perlu, memoles wajah agar terlihat lebih mempesona, disertai simbol dan atribut yang merepresentasikan makna dari motif yang diinginkannya. Seakan-akan peran yang dilakoni itu merepresentasikan karakter manusia yang diidealkan.

Kala berhadapan dengan rakyat miskin, mereka hadir laksana sinterklas dengan penampilan yang merakyat. Cara mereka berkomunikasi juga disesuaikan dengan bahasa keseharian masyarakat. Sementara kala berada di lingkungan elit, mereka tampil dengan gaya borjuis dan menggunakan bahasa yang lebih intelek. Dengan begitu, mereka dikesankan sebagai sosok yang sukses, pintar, berwibawa, dan berkharisma.
Namun, apakah cukup peran tersebut mendongkrak citra? Apalagi, motifnya untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan? Tentu tidak. Rasionalitas masyarakat dapat menilai orisinalitas karakter dan perilaku yang diperlihatkan para kandidat.
Di panggung suksesi, masyarakat bukan sekadar penonton pasif. Mereka aktif dalam mengais informasi seputar rekam jejak para kandidat dengan memanfaatkan berbagai saluran informasi. Pengetahuan itu yang dijadikan referensinya dalam menentukan pilihan politik.
Menempuh Cara Instan
Politik memang tidak bisa dilepaskan dari citra. Tetapi, untuk mendongkrak citra, tidak hanya dengan memoles rupa, penampilan, maupun tiba-tiba menjadi penderma. Citra terbangun karena persepsi, impresi, dan perasaan masyarakat terhadap kandidat. Itu terbentuk setelah menilai reputasi, rekam jejak, kompetensi, dan integritas para kandidat.
Cara-cara instan dengan menebar iklan pencitraan memang dapat mengerek popularitas sang kandidat. Tak salah pula jika cara demikian yang dilakukan. Toh, mereka punya banyak uang. Namun, cara-cara demikian yang menyebabkan biaya politik tinggi menjulang. Dan, masyarakat pun akan terus-terusan mempersepsikan bila perhelatan suksesi sebatas rekreasi politik, di mana ada kerumunan massa, suguhan hiburan, dan banjir bantuan.
Dan, apakah efektif cara demikian mempengarui pilihan politik warga? Jangan sampai usai suksesi digelar, mereka yang kalah menjadi gila karena uang dan hartanya terkuras untuk membiayai kampanye, mengongkosi tim sukses, dan relawan, termasuk membayar mahar ke partai politik pendukungnya.
Fenomena demikian sudah terjadi. Di Pemilihan Umum (Pemilu) sebelumnya, sejumlah calon legislatif yang gagal, melakukan beragam cara yang bikin geleng-geleng kepala. Mereka stres, bahkan ada yang nekat bunuh diri.

Di Nabire, Papua, calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN), Anselmus Petrus Youw, menutup jalan masuk ke perumahan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan balok kayu. Dia nekat melakukannya karena warga tidak memilihnya. Padahal, mantan bupati Nabire itu sudah memberikan tanahnya untuk pembangunan perumahan itu.
Di Tulungagung, Jawa Timur, Miftahul Huda, calon legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menarik kembali sumbangan material untuk pembangunan mushola karena gagal menjadi wakil rakyat. Di Kabupaten Cirebon, Witarsa Winata, calon legislatif dari Partai Demokrat, stres setelah gagal menjadi anggota DPRD Jawa Barat. Padahal, modal yang dikeluarkannya sangat besar. Dia mengaku pusing dengan tagihan utang sebesar Rp300 juta.
Bahkan, yang lebih tragis, ada yang bunuh diri. Di Ciamis, Jawa Barat, seorang ibu muda berinisial S yang gagal menjadi anggota DPRD Kota Banjar, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mayatnya ditemukan di saung bambu di Dusun Limusnunggal, Desa Bangunjaya, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Ciamis.
Itu baru calon anggota legislatif, yang secara modal finansial tidak begitu besar dibandingkan calon kepala daerah yang berlaga di ajang Pilkada. Bayangkan saja, ada calon kepala daerah yang harus mengeluarkan dana sebesar Rp100 miliar untuk menjadi kepala daerah.
Padahal, jika dikalkulasikan, selama lima tahun menjabat, gaji kepala daerah tidak menutupi modal yang telah dikeluarkan sebesar itu. Gaji gubernur hanya Rp8,4 juta per bulan, dan bupati atau walikota Rp5,8 juta per bulan. Jika dikalkulasikan selama lima tahun masa kerjanya, maka total gaji gubernur berkisar Rp510 juta dan bupati atau walikota, hanya Rp384 juta.
Bagaimana mungkin seorang calon kepala daerah rela menggelontorkan uang sebanyak itu? Apakah dia sudah kebanyakan uang? Atau yang bersangkutan benar-benar ingin mengorbankan hartanya untuk kepentingan masyarakat? Tak mungkin. Tak ada makan siang gratis (no free lunch) di panggung politik negeri ini.
Ada motif yang menyelip di balik pencalonannya. Setelah berhasil memenangkan suksesi, sosok yang tadinya penderma, berubah buas menggasak uang negara. Dia menjadi buas selama periode kepemimpinanya karena dibayangi niat mengembalikan modalnya. Kekuasaan pun disalahgunakan untuk mengeruk upeti.
Iklan pencitraan yang bertaburan, umumnya mengklaim peduli pada rakyat. Dampaknya, memang dapat meningkatkan popularitas sang kandidat. Wajar, karena masyarakat tak bisa menghindar dari penampakan iklan yang mencolok dan bertaburan di sepanjang jalan.

Namun, belum tentu iklan-iklan itu mempengarui pilihan politik warga. Masyarakat justru dibuat bingung karena semua kandidat pasti mengklaim hal yang sama. Bahkan, masyarakat cenderung resisten karena iklan-iklan itu merusak keindahan ruang-ruang publik. Alih-alih mendongrak citra, yang terjadi justru sebaliknya.
Karenanya, tingginya popularitas kandidat, kadangkala tidak berbanding lurus dengan pilihan politik warga. Itu mengindikasikan jika kampanye politik bukan sekadar perang iklan pencitraan. Pilihan politik warga juga tidak begitu saja dipengarui dengan uang yang ditebar para kandidat.
Dibutuhkan ikhtiar yang melelahkan disertai pembuktian. Prosesnya pun membutuhkan waktu yang cukup panjang. Diperlukan pula cara yang efektif, tepat sasaran, murah, dan mencerdaskan. Caranya, dengan mengoptimalisasikan modal sosial (social capital) yang sudah lama dibangun para kandidat. Modal sosial itu adalah reputasi, prestasi, rekam jejak dan kapasitas yang mumpuni serta integritas yang terbukti. Termasuk, mengelola dukungan dari jejaring sosial agar turut mempromosikan pencapaiannya.
Proses penetrasi yang paling efektif adalah dengan berinteraksi langsung ke tengah warga. Dengan begitu, kandidat dapat lebih optimal menyampaikan pesan dan menyakinkan komitmennya kepada warga. Di hadapan warga, kandidat juga tak hanya mengumbar senyum dan bersalaman. Dia harus mampu menawarkan solusi dan perubahan yang diharapkan masyarakat.
Namun, bukan berarti menggurui. Karena, warga yang lebih paham dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi di lingkungannya. Kandidat yang cerdas bukan berarti cakap berretorika. Namun juga menjadi pendengar yang baik kala masyarakat menyampaikan pendapat dan kehendaknya.
Selama ini, kampanye politik cenderung disimplikasikan hanya pada periode tertentu yang ditetapkan penyelenggara pemilihan umum (Pemilu). Kampanye politik juga dipahami sebatas aktivitas pengumpulan massa, orasi politik, pemasangan atribut kandidat dan partai maupun penyebaran iklan-iklan politik.
Dalam waktu yang ditentukan itu, para kandidat bersama partai politik pendukung, tim sukses, dan relawannya, dituntut untuk memaksimalkan sosialisasi visi misi dan program kerja. Namun, apakah dengan waktu yang singkat itu bisa mempengarui pilihan politik warga?

Seharusnya, kampanye politik tidak hanya menjelang suksesi. Namun, sebagai bagian dari komunikasi politik, kampanye dilakukan jauh hari dan berkelanjutan. Dan, orientasinya tidak sekadar menuai simpati. Namun, diarahkan untuk melakukan kerja-kerja advokasi.
Bagi mereka yang berada dalam sistem politik, baik itu di legislatif maupun eksekutif, komunikasi politik ditujuan untuk membangun investasi politik. Itu bisa dilakukan jika mereka mampu merespon masukan dari masyarakat yang kemudian dikonversikan dalam bentuk kebijakan maupun program yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.
Jika itu dilakukan dan dampaknya dirasakan masyarakat, maka akan membentuk brand personality. Semakin kuat brand itu melekat dalam diri politisi, maka akan kian menancap di benak masyarakat yang kemudian menjadi basis konstituennya.
Reputasi Bukan Manipulasi
Dalam dunia pemasaran, brand melekat pada sebuah produk yang dipasarkan. Kekuatan brand sangat berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Brand itu terbentuk lewat pengalaman konsumen. Sebelum membeli produk, konsumen umumnya mencari beragam informasi seputar kualitas dan manfaat produk itu (benefit).
Setelah menggunakan produk itu, konsumen pun membandingkannya dengan produk lain yang fungsi dan manfaatnya sama. Jika produk itu dirasakan manfaatnya, maka konsumen enggan beralih ke produk lain yang sejenis. Dia akan menjadi konsumen setia.
Menurut The American Marketing Association (AMA) seperti dikutip Keller, Aperia, dan Georgson dalam buku: Strategic Brand Management: A European Perspective (2008), brand dipahami sebagai nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi yang mengidentifikasi antara penjual barang dan jasa dengan yang lainnya. Brand juga untuk membedakan sebuah produk dari kompetitornya. Dengan kata lain, brand tak hanya menyangkut simbol dan atribut. Tetapi, mengandung makna yang kompleks, termasuk di antaranya adalah manfaat.

Dalam konteks persaingan bisnis, brand disesuaikan dengan dinamika pasar dan kebutuhan konsumen. Karenanya, dibutuhkan rebranding. Menurut Laurent Muzellec dan Mary Lambkin dalam bukunya: Corporate Rebranding: Destroying, Transferring or Creating Brand Equity (2004), rebranding adalah pembaruan yang perlu dilakukan untuk menghadapi pesaing baru. Rebranding juga dilakukan karena citra dan image sebuah produk saat ini sudah kadarluarsa sehingga perlu penyesuaian. Tujuannya untuk mempertahankan loyalitas konsumen.
Di sinilah pentingnya berpolitik dengan menerapkan cara-cara pemasaran di dunia bisnis. Persepsi positif masyarakat sebagai konsumen terhadap politisi sebagai produk, akan terbentuk jika politisi berhasil menyakini kualitasnya. Dengan kata lain, kehadirannya dirasakan manfaat bagi masyarakat. Jika itu berhasil, maka akan mempererat hubungan antara politisi dengan masyarakat. Bahkan, akan memunculkan loyalitas dan kesetiaan (brand loyality). Itu terbentuk karena kepercayaan (trust).
Dengan demikian, citra positif seorang kandidat terbentuk setelah masyarakat melihat, mengamati, mendengar, dan merasakan manfaat selama dirinya diberikan kepercayaan. Manfaat itu diwujudkan dalam bentuk keberhasilan sang kandidat dalam mendorong birokrasi yang melayani, profesional, dan bersih dari korupsi. Bisa pula keberhasilan sang kandidat di bidang lain.
Jika manfaat itu tidak dirasakan masyarakat, atau bahkan memunculkan kesan negatif, jangan berharap kandidat tersebut dipilih lagi. Kecuali, kandidat itu melakukan cara-cara manipulatif, melakukan politik uang (money politic) atau mempengarui indepedensi penyelenggara Pemilu.
Dalam politik, rebranding bisa dipahami sebagai perubahan, baik dalam strategi politik, perilaku dan budaya politik, orientasi, misi dan visi, dan program kerja. Tujuannya agar brand yang melekat pada kandidat lebih disukai masyarakat.
Dalam konteks politik kekinian, ada pemicu (triggering) yang menuntut politisi melakukan rebranding. Tuntutan itu karena perubahan persepsi masyarakat, kekuatan dan kelemahan kompetitor, termasuk potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Rebranding itu bisa diarahkan dalam penyusunan misi dan visi, program kerja, maupun rencana strategis yang berbasis kebutuhan masyarakat.
Dengan begitu, kandidat menawarkan program yang memberikan manfaat nyata. Bukan sekadar janji-janji surga. Dan, jika diwujudkan dengan baik, akan menjadi brand loyality, di mana masyarakat akan tetap mempertahankannya sebagai pemimpin. Mereka merasa tidak sia-sia mengamanatkan kepercayaan padanya.
Menyambangi Warga
Kampanye yang dilakukan para kandidat harus benar-benar menyakinkan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan kedekatan hubungan. Kedekatan itu bisa terbangun jika ada trust. Lantas bagaimana membangun trust? Sementara mereka yang bertarung di Pilkada belum pernah diberikan mandat memimpin di ranah pemerintahan. Apalagi, kandidat itu adalah sosok yang dianggap "terasing" dari daerah yang akan dipimpinnya. Apa mungkin bisa? Bisa saja.
Tetapi, membutuhkan kerja ekstra. Tak ada cara lain dengan membangun interaksi dengan masyarakat. Keberhasilan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam mengalahkan pasangan petahana Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli di ajang Pilkada DKI Jakarta, dapat menjadi referensi bagi pasangan kandidat non petahana.

Kala Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu, Jokowi-Ahok melakukan strategi sepakbola Spanyol, tiki-taka. Strategi itu menekankan soliditas tim dalam melakukan penetrasi. Lewat kepiawaian mengutak-atik bola, umpan-umpan pendek yang matang, dan kekompakan tim yang sangat luar biasa, Tim Matador yang diarsiteki Vicente del Bosque, berhasil membombardir gawang Italia yang dijaga Gianluiqi Buffon, dengan skor telak, 4:0.
Strategi itu diterapkan Jokowi bersama partai pendukung, tim sukses, dan relawannya. Sebagai sebuah tim, mereka melakoni perannya masing-masing. Caranya, dengan intensif menyambangi warga ibukota di kampung-kampung kumuh, di sekitar sungai Ciliwung, mengunjungi para pedagang dan konsumen di pasar-pasar tradisional, dan tempat-tempat lainnya.
Kepada warga yang disambanginya, mereka menebar umpan-umpan manis berupa program kerja dan janji-janji menyakinkan, yang diracik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga. Dengan harapan, warga mengeksekusi umpannya itu ke sasaran, yaitu memilih dirinya di Pilkada DKI Jakarta. Dan, hasilnya fantastis. Jokowi-Ahok berhasil memenangkan pertarungan di Pilkada DKI.
Bagi masyarakat, simpel saja dalam menentukan pilihan politik. Selain dengan mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi, dan integritas, masyarakat cenderung menyukai kandidat yang dirasakan dekat dengannya. Kedekatan itu bisa terbangun jika kandidat mendengar keluhan dan menyampaikan komitmen maupun janjinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
Masyarakat juga merasa dihargai dan tersanjung disambangi kandidat. Mereka juga sangat senang bisa ketawa-ketiwi bersama, bersalaman, apalagi diajak berdiskusi bersama menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi. Dengan begitu, kampanye akan lebih edukatif.

Lalu, dari pengalaman yang menyenangkan itu, mereka akan bercerita kepada keluarga, saudara, dan teman-temannya. Dengan begitu, secara tidak langsung, mereka menjadi agen kampanye untuk menyampaikan pesan politik kandidat kepada warga lain.
Bagi kandidat, berinteraksi langsung dengan warga juga penting guna mengetahui kondisi dan persoalan yang dihadapi warga. Dengan begitu, dia akan lebih mudah menyusun strategi pemenangan, misi visi, dan program kerja yang berbasis kebutuhan.
Karenanya, tepat jika mereka yang bertarung di ajang suksesi saat ini, telah jauh hari menyambangi warga yang ada di daerah kumuh, di pasar-pasar, di berbagai komunitas, dan tempat-tempat umum lainnya. Jadi, bukan dengan cara instan. Menjadi lucu jika melihat kandidat yang mendadak menjadi alim, merakyat, ramah, dan pemurah.
Selain itu, untuk lebih memaksimalkan penyampaian pesan kepada khalayak, maka kandidat perlu hubungan baik dengan media. Tetapi, tidak dengan mempengarui indepedensi wartawan. Harus diakui, kandidat yang menjadi media darling sangat diuntungkan di ajang suksesi. Kemenangan Jokowi di laga suksesi, tidak terlepas dari peran media. Pemberitaan soal sepak terjang Jokowi begitu gencar karena media memandang ada nilai berita (news value). Misalnya, kala menjabat sebagai Walikota Solo, media mengulas perseteruannya dengan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.
Keduanya berseteru terkait rencana pembangunan mal di atas lahan bangunan kuno bekas pabrik es Saripetojo, Kampung Jantirejo. Jokowi menentang pembangunan mal itu akan mengancam nasib pedagang kecil yang sudah lama berdagang di sekitar kawasan itu. Jokowi ingin bangunan itu dipertahankan sebagai cagar budaya karena sudah dibangun sejak tahun 1888. Dalam polemik itu, media cenderung mendukung Jokowi yang menolak pembangunan mal itu. Dari pemberitaan media, Jokowi pun dikesankan sebagai pemimpin yang berpihak kepada masyarakat kecil dan menengah, mengutamakan kepentingan pedagang kecil, dan mencintai warisan sejarah. Jokowi juga pandai melakoni peran sebagai pemimpin yang merakyat, ndeso, dan mampu menyakinkan akan komitmennya untuk kepentingan masyarakat luas.
Di sinilah pentingnya membangun hubungan yang baik dengan media, tanpa harus memanjakan media dengan memasang iklan. Hubungan dengan media dapat berjalan dengan baik jika ada keterbukaan kandidat terhadap wartawan. Media perlu dijadikan mitra berdiskusi, tanpa harus mengajak berkoalisi.

Namun, dengan membangun relasi yang saling menghargai profesi masing-masing. Misalnya, memberikan kemudahan bagi wartawan untuk mewawancarai atau mengakses data dan informasi yang penting diketahui publik. Meski demikian, harus diakui, sebagai instrumen yang mengonstruksikan persepsi khalayak, media tidak bebas nilai sehingga bias dan berpihak. Itu terlihat dari framing pemberitaannya.
Pertarungan Destruktif di Media Sosial
Media sosial telah menjadi medium bagi masyarakat untuk mempraktikan politik partisipatif. Lewat media sosial, masyarakat dapat terlibat dalam diskursus yang mengulas isu dan dinamika politik serta mempengarui kebijakan-kebijakan publik.
Masyarakat juga rada melek politik karena disuguhkan informasi politik yang bertebaran di dunia maya. Sebagian di antara masyarakat juga suka mengikuti desas-desus politik yang berseleweran di dunia maya Sementara bagi politisi, media sosial dapat menjadi saluran menyampaikan pesan politik, termasuk merespon aspirasi publik.
Di era digital dewasa ini, peran media sosial dalam membentuk persepsi publik, seakan menggilas media mainstream. Efeknya sangat luar biasa karena penggunaan media sosial jumlahnya signifikan.
Barrack Obama adalah contoh politisi yang sukses mencapai puncak kekuasaan karena mengoptimalkan peran media sosial. Kala Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) digelar tahun 2008, Obama beserta timnya, begitu intensif menyampaikan pesan-pesan politik lewat Facebook, My Space, Youtube, dan sebagainya. Bahkan, video game pun menjadi alat kampanyenya.
Lewat media sosial, warga AS juga dapat menanggapi berbagai pesan kampanye politik yang disampaikan Obama. Mereka juga dapat mengais referensi secara komprehensif seputar rekam jejak, misi, visi, dan program kerja Obama jika menjadi Presiden AS.
Pun halnya dengan Jokowi. Kemenangannya di ajang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 maupun di ajang Pemilihan Presiden 2014, tidak terlepas dari intensifnya kampanye di ranah maya.
Kampanye itu diorganisir oleh relawan yang tergabung dalam Jasmev. Mereka melakoni peran sebagai influencer, twitter war, atau bergabung dalam offensive team. Mereka dibekali teknik dan pengetahuan untuk melakukan balasan (counter) terhadap isu-isu negatif yang menyerang Jokowi. Mereka juga aktif menjawab setiap pertanyaan yang diajukan penghuni dunia maya terkait rekam jejak Jokowi.

Di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, kampanye Jokowi dan Ahok, begitu intensif di dunia maya. Itu dilakukan karena begitu banyak jumlah pengguna media sosial di ibukota. Pengguna Twitter misalnya. Hasil riset Semiocast yang berbasis di Paris, Perancis menunjukan, Jakarta sebagai kota paling "berisik" di dunia. Jumlah pengguna Twitter di Jakarta mencapai 10 juta orang, mengalahkan New York (AS), Tokyo (Jepang), London (Inggris), dan Sao Paolo (Brazil).
Jakarta juga paling banyak pengguna Facebook. Sampai-sampai, Peter Vesterbacka, Chief Marketing Officer Rovio menyebut, Jakarta sebagai ibukota Facebook. Dari data yang dirilis socialbakers.com, pengguna Facebook di Jakarta mencapai 17,48 juta orang. Di media sosial juga ada Google+, LinkedIn, Istagram, Youtube, dan sebagainya. Semua aplikasi itu dapat dimanfaatkan secara gratis untuk kampanye politik.
Sayang, pertarungan politik di dunia maya cenderung destruktif. Pasukan dunia maya (cyber troops) yang dikerahkan kandidat cenderung menjejali media sosial dengan opini yang terkesan saling menghinakan. Demi membela junjungannya, cyber troops menebar caci maki, pembusukan, dan kalimat-kalimat yang tidak patut. Mereka juga menebar meme, gambar yang disertai kutipan kalimat-kalimat pendek yang bernada satir untuk memojokan lawan politik atau siapa saja yang "bersenggolan" dengan jagoannya.
Seharusnya, cyber troops memanfaatkan media sosial sebagai sarana menggalang partisipasi politik warga dan menebar pesan-pesan edukatif. Bukan justru menebar opini destruktif yang dapat membelah masyarakat.
Relawan Bukan Tim Hore
Dalam memenangkan pertarungan, kandidat membutuhkan peran relawan. Menjamurnya relawan di ajang suksesi menjadi hal positif bagi demokrasi. Peran mereka tak kalah penting dibandingkan partai politik. Mereka bergerak dari kampung ke kampung dan mengorganisir dukungan masyarakat.
Sayang, peran relawan lebih dominan menjadi "tim hore" yang meramaikan kampanye. Mereka juga lebih sibuk melakukan pembusukan ke lawan politiknya, mengorganisir pengerahan massa, dan membagi-bagikan sembako kepada warga.

Seharusnya, mereka lebih mengoptimalkan kampanye yang mencerdaskan, solutif, inspiratif, kreatif, dan simpatik. Relawan harusnya memfasilitasi kampanye dialogis antara warga dengan kandidat untuk membahas berbagai persoalan bersama-sama. Bisa pula dengan menggelar diskusi kelompok (group discussion), di mana relawan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara warga dengan kandidat. Dengan begitu, terbuka ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi pesan, isu, atau program yang ditawarkan para kandidat.
Relawan juga dituntut mampu menjadi komunikator yang baik, yang cakap dalam menyampaikan pesan-pesan politik sehingga mudah dicerna masyarakat. Proses komunikasi itu bisa berlangsung efektif jika relawan memahami kondisi yang dihadapi masyarakat. Di sinilah pentingnya relawan mengindentifikasi realitas objektif di masyarakat. Mereka juga perlu memahami karakteristik dan preferensi pemilih.

Dalam konteks sosiologis, preferensi pemilih terkait karakteristik, pengelompokan sosial dalam masyarakat, maupun ikatan sosial, baik dari struktur sosial, interaksi sosial, etnik, ras, agama, keluarga, dan sebagainya.
Perilaku pemilih juga cenderung dipengaruhi nilai, norma, kepercayaan dan sebagainya. Nilai dan norma menjadi faktor yang bisa mempengarui perilaku masyarakat karena menjadi rujukan, petunjuk, atau arah bagi masyarakat dalam bersikap, bertindak, dan mengontrol tindakannya. Nilai dan norma juga menjadi instrumen pemersatu masyarakat.

Sementara dalam konteks psikologis, perilaku pemilih terkait loyalitasnya terhadap kandidat dan partai politik. Namun, bukan berarti mereka mengabaikan evaluasi terhadap rekam jejak masing-masing kandidat. Menghadapi masyarakat demikian, membutuhkan komunikasi yang intensif dan kecakapan dalam menawarkan program yang berbasis pada kebutuhan. Itu penting karena rasionalitas pemilih dipengarui realitas objektif.
Para pemilih rasional juga menentukan pilihan politik berdasarkan referensi. Mereka tidak percaya dengan janji-janji yang ditawarkan para kandidat. Mereka memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, dan informasi. Dalam menghadapi pemilih rasional, relawan dituntut menguasai persoalan dan memiliki argumentasi berbasis data untuk menyakinkan pemilih. Jadi, bukan sebatas "cuap-cuap" mempromosikan kelebihan jagoannya.
M. Yamin Panca Setia