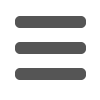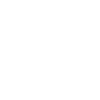Pendekar Mabuk di Tengah Coronastrope

Bang Sém
Karena tak punya imajinasi tentang Indonesia tiga dekad ke depan, dan hampir satu dekad terjebak dalam fantasi berlumpur utang, plus remang pekatnya coronastrope (petaka virus corona), banyak kalangan memilih hidup sebagai campers. Tak punya daya untuk menjadi hikers, apalagi climbers.
Dinamika perubahan cepat yang berlangsung di tengah masyarakat (lokal, regional, global) yang tertakluk oleh coronastrope, dan membawa perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya, mengubah orientasi nilai hidup di segala lapisan.
Perubahan-perubahan itu didorong oleh rontoknya nilai -nilai global yang dimakan oleh produk budaya sendiri (khasnya kemajuan teknologi informasi). Perubahan ini membentuk sikap, pandangan, tujuan, dan gaya hidup masyarakat.
Tragisnya, negara-negara dan bangsa-bangsa ironik sekaligus ambivalensia -- yang memiliki banyak petinggi, tapi miskin pemimpin; banyak akademisi, tapi miskin intelektual; banyak politisi, tapi miskin negarawan; banyak pebisnis, namun miskin entrepreneur; banyak pemuka agama, tapi miskin kesalehan; banyak aktivis, tapi tak lebih dari kerumunan -- telah menjadi korban salah memilih jalan perubahan reformasi. Perubahan melelahkan menuju deformasi (perubahan bentuk yang dipengaruhi berbagai distorsi dan depresi).
Negara-negara dan bangsa-bangsa ironik tersebut, hidup dalam ombang khayali: kaya sumberdaya alam, besar populasi penduduknya (namun hanya menjadi sumberdaya manusia, bukan modal insan), yang terus menerus diekploitasi dan rakyatnya miskin persisten. Mereka hidup di titik nadir karena paradoksnya kemakmuran dengan keadilan.
Dalam situasi 'lelah sosial,' dan kebuntuan semacam itu, banyak kalangan, mencari katarsis sosial dan menjadi kaum campers, bersunyi-sunyi dan berhening-hening, dan merasa nyaman pada posisi tertentu dan enggan mendaki mencapai puncak kehidupan yang sesungguhnya.

Tak banyak yang memilih hidup sebagai climbers -- manusia pendaki yang berpandangan visioner, mampu mengelola spirit dan energinya secara mankus dan sangkil (efektif dan efisien), kreatif, inovatif, konsisten, konsekuen, sangat optimistis, berani menghadapi dan mengambil risk dengan perhitungan matang dalam mengenali kelemahan, sehingga mampu merumuskan kekuatan yang harus dimiliki dalam menghadapi tantangan dan ancaman, untuk mendapatkan berbagai peluang.
Bilangan mereka tak jauh beda dengan mereka yang mengubah dirinya dari sumberdaya manusia menjadi modal insan yang mengembangkan modal sosial, yakni para hikers. Para pejalan jauh yang berani menembus semak belukar kehidupan dengan perhitungan matang, terencana baik, perfect, konsisten berjalan pada track, dengan aksi yang terukur dalam kiat dan siasat, namun konsekuen dengan niat dasar kehidupannya.
Dalam buku Indigostar (2009), saya memasukkan manusia dengan tipe climbers dan hikers, adalah mereka yang menapaki jalan taqwa. Manusia yang tak pernah henti melaksanakan seluruh proses kehidupan dan penghidupannya, baik secara individual, komunal, maupun sosial, baik di dalam atau di dalam organisasi (institusi) sebagai ibadah, meski dengan sedikit ilmu dan keahlian.
Mereka termasuk ke dalam kategori manusia yang abid dengan tenaganya. Manusia yang berpendirian, tak terikat oleh fungsi maupun posisinya di dalam suatu struktur organisasi atau lembaga.
Mereka bukan manusia yang diombang-ambingkan laksana nyamuk kecil terbuai pawana, yang hidup di alam ilusi dan fantasi, sehingga seringkali terjebak menjadi manusia individualis yang menjalani hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Manusia, yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan memenuhi hasrat dan kepentingannya sendiri. Lalu, cenderung menempatkan dirinya hanya sebagai follower bagi patron-nya, meski seringkali merasa diri sebagai pemimpin, leader.
Mereka termasuk golongan manusia yang memandang loyalitas, dedikasi, solidaritas dan soliditas hanya kepada manusia semata. Bukan kepada cita-cita terbaik, visi maupun misi kolektif organisasi yang disepakati bersama. Karena itu, mereka mudah terperosok sebagai manusia yang menggantungkan hidupnya kepada keadaan, bukan kepada Allah subhanahu wa ta’ala.

Di dalam kehidupan modern kini dan mendatang, di tengah proses kehidupan yang tak pernah luput dari hadangan krisis, turunan kualifikasi manusia semacam itu, menjadi lebih beragam. Bagi mereka yang berada dalam kualifikasi intelektual yang saleh dan bertaqwa, yang selalu menjadi pusat perhatiannya dalam menghadapi kehidupan dan penghidupan (baik saat lapang maupun saat peluang kian sempit adalah menemukan solusi-solusi. Tak henti melakukan ikhtiar optimistis.
Dalam konteks itu, manusia selalu dituntut untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat -- from the vaginal hole to the grave. Maknanya adalah hidup merupakan rangkaian panjang aktivitas berlatih. Bagi seorang pendekar, hidup adalah kultivasi benih watak manusia dalam menghadapi dimensi rasional - realistis dan dimensi liar - ilusionis. Karenanya, sesuatu yang berkaitan dengan nalar - nurani - naluri - dan rasa membentuk integritas diri, sehingga manusia mempunyai keseimbangan - harmoni dalam mengendalikan diri. Termasuk dalam hal mengendalikan senjata pembunuh.
Dalam jagad kependekaran ada yang disebut sebagai pedang mabuk, drunken swords - pedang di tangan pendekar mabuk. Pedang di tangan pendekar derhaka yang hanya melihat master pendekar Tao kerap membawa kantung arak, tanpa mencari tahu apa tujuannya.
Di tangan Tao, arak selalu dibawa untuk kepentingan mengobati dirinya bila terluka dan untuk kepentingan relaksasi otot-otot, karena Tao dan para muridnya adalah kaum hikers, yang melakukan perjalan pendakian yang panjang dan jauh mencapai puncak.
Para 'pendekar' menggunakan arak untuk mabuk-mabukan. Dalam keadaan mabuk, itulah mereka menari dengan mengayunkan pedang, sehingga banyak memakan korban. Celakanya, dalam keadaan mabuk, mereka merasa pedang menyatu dengan dirinya, seperti manusia menyatu dengan alam.
Kalangan akademisi yang sibuk dengan teks dan gagap menghadapi konteks merumuskan pendekar mabuk (drunken master) beserta pedang-nya dengan rumusan lebih berbahaya. Menghadirkan teori-teori memabukkan yang akan membuat para 'pendekar' terhuyung-huyung. Lupa pada esensi, bahwa keberanian, kesabaran, dan ikhtiar mendapatkan solusi dalam menghadapi situasi krisis dan kritis adalah kunci pokok.

Keberanian hidup diutamakan, keselamatan manusia didahulukan. Inilah kekuatan yang utama, di balik esensi di balik kesulitan selalu ada inspirasi, di balik kelemahan tersedia kekuatan yang sesungguhnya, untuk menuntaskan sesuatu tugas - kewajiban, sebelum melanjutkan dengan tugas - kewajiban berikutnya.
Senjata -- dalam pengertian harafiah atau metafor, konotatif dan denotatif, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi -- dengan kematangan dan keseimbangan nalar - nurani - naluri dan rasa yang membentuk ketabahan dalam menemukan momentum untuk menyerang dan menerjang dalam sekejap, menjadi lebih besar manfaatnya katimbang madharatnya.
Senjata di tangan manusia yang memilih jalan taqwa, dalam jagad persilatan mempertemukan yin (gerakan lembut) dan yang (keteguhan - ketabahan) menjadi sangat ampuh dalam menghadapi zaman yang tidak pasti, bersimbah keraguan, keribetan, dan keterbelahan.
Saya membayangkan, kini kita sedang menyaksikan para 'pendekar mabuk' yang menggunakan senjatanya dengan memisahkan yang dengan yin. Khasnya dalam memantik dan mencungkil reception dan perception khalayak dalam proses berpikir yang sesat. Antara lain, menempatkan rakyat dan penguasaan (ownership), yang disajikan dalam kalimat 'rakyat milik presiden.' Suatu kepandiran yang gelap, ketika khalayak meraba remang untuk menemukan titik cahaya harapan kala berjalan di lorong kegamangan.
Para 'pendekar mabuk' itu hanya menggunakan senjata sekadar menunjukkan keterampilan fisik seolah-olah sedang berfikir, padahal sedang melayang dalam ilusi. Dampaknya, berkecambahkan sikap negatif dalam mengelola negara. Mereka terbilang kaum yang lebih senang memainkan 'pedang mabuk' dan igauan di sekitar tenda perkemahan, katimbang terus melangkah dan mendaki mencapai puncak pencapaian, gerbang husnul khatimah.
Dalam konteks ini, kita tak boleh diam. Paling tidak, kita mesti menyanyikan atau meneriakkan kembali esensi syair Kesaksian, Rendra (1990) :
Aku mendengar suara / Jerit makhluk terluka / Luka, luka / Hidupnya / Luka // Orang memanah rembulan / Burung sirna sarangnya / Sirna, sirna / Hidup redup / Alam semesta / Luka // Banyak orang Hilang nafkahnya / Aku bernyanyi / Menjadi saksi // Banyak orang dirampas haknya / Aku bernyanyi / Menjadi saksi // Mereka / Dihinakan / Tanpa daya / Terbiasa hidup / Sangsi // Orang orang Harus dibangunkan / Aku bernyanyi / Menjadi saksi / Kenyataan / Harus dikabarkan / Aku bernyanyi / Menjadi saksi // Lagu ini / Jeritan jiwa / Hidup bersama / Harus dijaga // Lagu ini / Harapan sukma / Hidup yang layak / Harus dibela //