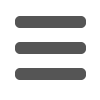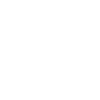Mudik, Disparitas Pembangunan Desa-Kota

JELANG perayaan Idul Fitri 1437 hijriah, jutaan orang, khususnya umat muslim di Indonesia, menjalani prosesi mudik. Mereka bergerak dari berbagai kota menuju kampung halamannya agar dapat merayakan lebaran bersama keluarga dan sanak saudara.
Mudik menjadi fenomena sosial yang unik. Ritual tahunan ini hanya terjadi di Indonesia. Dalam Islam, tidak dikenal mudik jelang Idul Fitri. Di Arab Saudi, tidak ada pula tradisinya. Di Amerika Serikat, prosesi mudik dilakukan saat perayaan Natal (Christmas Day) maupun Thanksgiving Day. Namun, mobilitas mudik di negeri Paman Sam tidak bersifat massal.
Meski tidak mengenal mudik jelang lebaran, Islam mengajarkan umatnya menjaga dan memperluas silaturahmi. Dalam konteks ini, mudik bisa dipahami sebagai "ikhtiar" untuk merealisasikan ajaran itu.
Meski sebenarnya, silaturahmi dapat dilakukan kapan saja, tanpa harus bertemu secara fisik dengan orang-orang yang dicintai. Apalagi, saat ini, sudah ada teknologi komunikasi yang dapat menghubungkan seseorang dengan orang lain, yang terpisah jaraknya untuk bersilaturahmi.
Namun, bagi sebagian besar muslim di Indonesia, silutarahmi di kala lebaran, kurang afdal jika tidak bertemu langsung, meminta maaf, bersalaman, mencium tangan orang tua atau saudara yang dituakan. Kepuasan batin akan lebih terasa tatkala bisa bercengkrama dan berbagi kebahagiaan di hari kemenangan bersama keluarga.
Perayaan Idul Fitri juga terasa hambar jika tidak bercengkrama dengan sanak saudara maupun teman-teman di kampung halaman. Persepsi itu yang kemudian seakan mewajibkan seseorang untuk mudik. Tak peduli jauhnya jarak yang ditempuh. Belum lagi ancaman keselamatan selama perjalanan. Peristiwa memilukan yang terjadi dalam prosesi mudik seperti di tahun-tahun sebelumnya tidak mempengarui keinginan seseorang untuk mudik.
Di tahun 2015, jumlah korban meninggal dunia mencapai 657 orang dan luka berat 1.939 jiwa. Sementara di tahun 2014, jumlah korban meninggal dunia mencapai 714 orang dan 1.068 orang yang mengalami luka berat. Tahun ini, jumlah pemudik diperkirakan mencapai lebih dari 26 juta jiwa. Tentu, semua berharap, mudik tahun ini bebas dari petaka, aman, lancar, dan nyaman.

Mudik berasal dari kata udik yang berarti hulu sungai, pegunungan, kampung atau desa. Konon, mudik sudah berlangsung sebelum jaman Kerajaan Majapahit. Dalam tradisi masyarakat Jawa kuno, mudik merupakan kegiatan ritual berupa ziarah ke makam para leluhur dan berdoa kepada para dewa agar diberikan keselamatan. Kini, selain bersilaturahmi dengan keluarga, mudik bertujuan agar dapat berziarah ke makam orang tua. Sementara ritual yang bersifat syirik dihilangkan sejak masuknya Islam ke Nusantara.
Tradisi mudik sebenarnya mengandung nilai yang patut dipertahankan. Misalnya, nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, saling memaafkan, tolong menolong, dan sebagainya. Seseorang, meski sudah sekian lama tinggal di tanah perantauan, tidak bisa begitu saja melepaskan ikatan emosional, baik dengan keluarga inti, keluarga besar, maupun rekan-rekan lamanya di kampung halaman. Dia juga kadang sulit melepaskan identitas asalnya.
Keinginan untuk mudik juga tidak terlepas dari dorongan mengenang masa lalu, mengenang kelucuan di kala masih anak-anak di kampung halaman. Mudik juga menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan rekreatif untuk mengusir penat setelah sekian lama bergelut dengan rutinitas kerja.
Namun, makna silaturahmi mengalami distorsi lantaran menjadi ajang menunjukan eksistensi diri, dengan menonjolkan simbol-simbol kemakmuran atau kesuksesan dalam bentuk materi seperti kendaraan, pakaian, membagi-bagikan uang, dan sebagainya. Dan, manusiawi juga jika setiap manusia tidak ingin dianggap gagal oleh orang lain.
Mudik tidak sekadar karena dorongan budaya semata. Namun, mudik adalah realitas yang mengambarkan adanya ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota. Karena, hampir sebagian besar para pemudik adalah orang desa atau orang daerah, yang migrasi ke kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya, Makassar, dan sebagainya, karena berharap mendapatkan sumber-sumber ekonomi. Mereka berbondong-bondong ke kota lantaran dianggap menjanjikan.
Di kota, banyak perusahaan dan pabrik-pabrik yang membutuhkan tenaga kerja. Sementara di desa, ketersediaan lapangan kerja sangat minim, lahan pertanian pun makin berkurang lantaran dikuasai segelintir pihak. Pendapatan dari sektor pertanian yang kurang menjanjikan menyebabkan menurunnya minat masyarakat desa, khususnya pemuda, untuk bertani. Ada juga yang alih profesi dari sektor pertanian menjadi buruh pabrik atau pekerja formal lainnya di kota lantaran lebih terlihat hasilnya.

Belum lagi keterbatasan infrastruktur seperti transportasi, pasar, sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan, menyebabkan masyarakat desa sulit berkembang. Kondisi serba kekurangan itu yang kemudian menstimulan warga desa untuk migrasi ke kota. Desa, dianggap mereka, bukan tempat yang menjanjikan bagi masa depannya.
Karenanya, jumlah penduduk di desa terus menyusut lantaran hijrah ke pinggiran kota. Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, jumlah penduduk Indonesia yang menetap di desa saat ini, hanya sekitar 50,2 persen dari total penduduk Indonesia. Berbeda di era tahun 1980-an, di mana sekitar 78 persen jumlah penduduk Indonesia menetap di desa. Di tahun 2025, diperkirakan, total penduduk Indonesia yang menetap di kota mencapai 70 persen di tahun 2025 dan 85 persen di tahun 2050.
Sumber-sumber ekonomi yang menumpuk di kota menjadi penyebab masyarakat desa migrasi ke kota. Arus migrasi yang tidak terkendali itu pada akhirnya munculnya beragam patalogi sosial di perkotaan seperti kriminalitas, pengangguran, kemiskinan, konflik, dan sebagainya.
Sementara bagi desa, migrasi yang tidak dikendalikan, akan menurunkan tingkat produktifitas desa. Sektor pertanian makin ditinggalkan lantaran banyak petani yang beralih menjadi buruh atau pekerja informal di kota. Akibatnya, dalam jangka panjang, akan mengancam ketahanan pangan (food security) yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial (social security), stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan nasional (national security).
Pemerintah telah menyadari jika paradigma pembangunan harus diubah, dengan lebih berorientasi pada desa. Dengan disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka diharapkan masyarakat desa dapat menjadi subyek, sekaligus penerima manfaat pembangunan. Pemerintah menyebutnya dengan paradigma "Desa Membangun".
UU Desa juga mengamanatkan kewajiban negara mengalokasikan anggaran desa. Nilainya sangat fantastis. Di tahun anggaran 2016, pemerintah dan DPR menetapkan alokasi anggaran desa hingga mencapai Rp46,9 triliun, naik dibandingkan tahun anggaran 2015 yang mencapai Rp20,76 triliun. Dana itu ditebar ke 74.754 desa.
Substansi yang terkandung dalam UU Desa sejalan dengan agenda prioritas ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, yang menekankan pembangunan Indonesia dari kawasan pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dengan lebih memusatkan perhatian ke desa, maka diharapkan disparitas pembangunan antara desa dengan kota dapat dipangkas.
Jika pembangunan desa dirasakan manfaatnya, maka masyarakat desa tidak perlu lagi ke kota. Sebaliknya, jika dari tahun ke tahun jumlah pemudik terus meningkat, maka bisa menjadi indikator jika keberhasilan pembangunan desa, baru sebatas klaim pemerintah saja.
M. Yamin Panca Setia