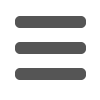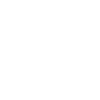Kota yang Melanggengkan Budaya Kemiskinan
AKARPADINEWS.COM | SUDAH enam tahun, Jajang bersama isterinya, Rositi, dan kedua buah hatinya, bertahan hidup di Jakarta dengan menjadi pemulung. Setiap hari, sejak pagi, Jajang menyusuri jalanan Jakarta bersama gerobaknya. Dia berjalan menuju Pasar Minggu, Pancoran, Tebet, hingga Manggarai.
Rezeki yang diraihnya terkadang naik turun. Kalau lagi beruntung, dalam waktu setengah hari, dia mendapat banyak kardus dan botol plastik, lalu disetorkan ke pengepul. Lalu, Jajang menerima upah Rp30-50 ribu. Namun, kadang setelah seharian, barang rongsokan yang dicarinya tak juga didapatkan. Dia pun menumpuknya terlebih dahulu, baru kemudian disetorkan ke pengepul. Lantaran tak memberikan setoran, Jajang pun tak dapat uang.
Dalam mengais rezeki, Jajang sering mengajak Rosita dan dua anaknya, Aprian (enam tahun) dan Anisa (dua tahun). Kedua bocah itu, bermain di dalam gerobak, di antara dus-dus dan botol-botol bekas. “Meskipun beban gerobaknya lebih berat, tapi hati lebih senang, gak khawatir sama anak-anak,” katanya.
Ketika Akarpadi mewawancarainya di perempatan dekat lampu merah Tebet, Jajang terlihat rada malu-malu mengkilas balik kisahnya enam tahun lalu. Baginya, tidak ada pendatang yang tidak memiliki mimpi untuk hidup lebih sejahtera ketika merantau ke Jakarta. Namun, tanpa ditopang pendidikan, keterampilan, dan jaringan yang luas, Jakarta menjadi kota yang kejam. “Jadi, dulu waktu anak pertama masih di kandungan, sulit sekali cari pekerjaan, jadi nekad saja ikut sama teman kerja di Jakarta. Ternyata, saya diajak bekerja jadi pemulung,” kenang laki-laki asal Jawa Barat tersebut.
Selain memulung, sesekali Jajang ikut kawannya yang mengajak menjadi kuli barang, ikut bongkar muat barang. Hasilnya, Jajang mengatakan, lumayan untuk tambahan jajan anaknya sekolah. Dalam sehari, Jajang rata-rata mendapatkan Rp50 ribu. Uang segitu, digunakan untuk makan bersama keluarga, plus jajan anaknya. Jika ada sisa, Jajang menabungkannya untuk bayar kontrakan dan sekolah anaknya. “Dicukup-cukupkanlah, untuk biaya hidup,” katanya sambil melirik sang istri.
Beberapa tahun silam, sebelum Jajang dan keluarganya mengontrak di kawasan pemukiman kumuh, di Gang Buntu 2, Pancoran, Jakarta Selatan, sang istri sempat merasa tak kerasan.
Pertama kali menginjakkan kaki ibu kota, Jajang dan keluarganya menumpang di bedeng milik bos pemulung. Di sana, mereka tidur beralaskan kardus. Kondisinya memprihatinkan. Kadangkala, tikus hilir mudik. Kamar mandinya pun kotor. Ruangan pun sumpek untuk dihuni.
Mengingat tempat itu, Rositi lalu berucap, “Jakarta itu sesak, sama seperti bedeng itu.” Lantaran tak kerasan, setiap malam, Rositi selalu ingat kedua orang tuanya di kampung. “Kenapa harus kayak begini Ya Allah. Rasanya sakit hati banget, orang tua saya di kampung pasti sedih kalau saya kerja kayak gini.” Karenanya, Rositi mengaku pada orang tuanya jika di Jakarta bekerja di sebuah restoran. Sementara suaminya, bekerja sebagai kuli bangunan. "Soalnya takut orang tua dan keluarga sakit hati kalau saya pemulung, jadi biar pahit manisnya, saya dan suami saja yang merasakan,” kata Rositi.
Di tengah beratnya hidup selama di Jakarta, Jajang dan Rositi sangat khawatir dengan masa depan anaknya. Mereka khawatir anak-anaknya tidak dapat melanjutkan pendidikan dan berkembang di lingkungan pergaulan yang cocok bagi anak-anak. Menurut Rositi, dia merasa lebih aman bila membawa anak-anaknya ikut bekerja dibanding harus diam di rumah.
Namun, dia mengakui, jika lingkungan turut mempengarui sikap dan perilaku anaknya. Misalnya, dalam berbahasa, anak sulungnya jadi sering mengikuti kata-kata kasar hingga bermain tanpa kenal waktu. Selain itu, Rositi kadang kerepotan jika anaknya ditinggal bekerja. “Kalau di rumah jam 10 atau 11 malam masih kelayapan. Jadi, harus dicari-cari dulu. Jadi mendingan dibawa kayak gini, keliatan langsung, kalau di rumah takutnya main ke jalan atau sampai diculik.”
Persoalan lain yang juga kerap dihadapi keluarga pemulung itu adalah perlakuan diskriminatif yang kerap dialami. Masalahnya, lantaran mereka tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Jakarta. Hingga kini, mereka masih menggunakan KTP dan kartu keluarga daerah asalnya.

Lantaran tak mengantongi identitas sebagai warga Jakarta, mereka sering kesulitan saat mengurusi administrasi untuk sekolah anak maupun saat mengajukan permohonan bantuan pendidikan atau kesehatan. Mereka cenderung dipersulit, bahkan sama sekali tidak mendapatkannya.
Bantuan-bantuan yang biasa diterimanya dari para donatur yang datang ke kawasan kumuh. Tetapi, bantuan itu pun lebih banyak masuk ke kantong para bos pemulung dan pemulung langganan para donatur. "Mungkin untuk yang gratis-gratis, kami belum ada rezekinya,” kata Jajang.
Ada keinginan Jajang dan istrinya menyekolahkan kedua anaknya di kampung halaman. Selain karena lingkungan di desa lebih baik, Jajang ingin anak-anaknya mengenyam pendidikan formal dan belajar agama. Keinginan itu akan diwujudkan Jajang setelah Anisa masuk sekolah. Jajang dan isterinya pun tak ingin berlama-lama tinggal di Jakarta. Kelak, bila sudah memiliki cukup uang, dia ingin isterinya membuka usaha warung kecil-kecilan di kampungnya. Sementara Jajang, akan menjalani hidup sendiri di Jakarta, mencari nafkah untuk keluarganya.
Perjalanan hidup Jajang dan keluarga, menunjukan jika tujuan para pendatang ke Jakarta adalah mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Namun, tanpa memiliki bekal pendidikan dan keterampilan, hidup di Jakarta, justru mengarahkannya makin terperangkap dalam lingkungan miskin dan tidak menyehatkan.
Jajang sendiri mengaku jika hidup di Jakarta tidak lebih baik dibandingkan hidup di desa. Dia harus tinggal di lingkungan kumuh dengan kondisi rumah yang tak layak. Berbeda di desa, yang lingkungan lebih sehat.
Di desa, kemiskinan lebih disebabkan karena minimnya lapangan kerja. Berbeda dengan kota yang menjanjikan banyak pekerjaan. Tetapi, tanpa berbekal pendidikan, keterampilan, pengalaman dan jaringan, para pendatang banyak yang tergilas oleh persaingan. Kejamnya ibu kota memaksa mereka untuk terus-terusan miskin.
Namun, kota, seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya, dengan pesonanya, senantiasa mampu menyedot minat orang-orang desa untuk mencari peruntungan. Persaingan pun semakin ketat seiring bertambah para pencari kerja. Dalam kondisi demikian, kota mengukuhkan realitas kemiskinan kepada para pendatang yang tidak mampu bersaing.
Oscar Lewis, antropolog yang membahas tentang budaya kemiskinan (cultural of poverty) mejelaskan, lebih mudah menghapuskan kemiskinan, dibanding budaya kemiskinan itu sendiri. Dalam konteks ini, budaya kemiskinan adalah adaptasi dan reaksi kaum miskin, di mana kebudayaan tersebut cenderung melanggengkan kemiskinan dari generasi ke generasi. Realitas itu akibat ketidakmampuan orang tua dalam menyekolahkan anaknya lantaran biaya yang mahal sehingga anak-anaknya miskin pengetahuan dan keerampilan.
Tanpa memiliki bekal pendidikan dan keterampilan, keringat mereka pun dihargai dengan upah yang murah. Lalu, mereka menikah, memiliki anak, yang kemudian anaknya pun miskin lantaran tidak menjalani pendidikan. Begitu seterusnya. Keluarga miskin itu memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berbeda, kemudian membentuk sub kultur sendiri.
Dengan begitu, kemiskinan tidak hanya karena kebijakan negara atau dominasi golongan elit yang melahirkan ketimpangan ekonomi dan marginalisasi sosial. Namun, lebih dari itu. Kemiskinan juga karena budaya kemiskinan, yang dijelaskan oleh Oscar dalam buku klasik Five Families: Mexican Case Studies in The Culture of Poverty (1959), di antaranya karena rendahnya semangat dan dorongan untuk meraih kemajuan, lemahnya daya juang dan motivasi untuk bekerja keras serta tingkat kepasrahan pada nasib yang tinggi maupn respon yang pasif dalam menghadapi kesulitan ekonomi.
Budaya kemiskinan juga berupa lemahnya aspirasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik, cenderung mencari kepuasan sesaat, berorientasi masa sekarang, dan tidak berminat pada pendidikan formal yang tinggi.
Karakteristik kebudayaan kemiskinan ini sangat bertolak belakang dengan karakteristik manusia modern di perkotaan yang mengutamakan kerja keras, dorongan untuk maju, pencapaian prestasi dan berorientasi masa depan. Jadi, faktor yang membentuk budaya kemiskinan ini adalah mentalitas orang miskin yang turut memberikan sumbangan pada problem kemiskinan. Jadi, bukan semata faktor eksternal maupun masalah struktural.
Berkaitan dengan kemiskinan di Jakarta, budaya kemiskinan adalah reaksi dan adaptasi masyarakat terhadap posisi marginalnya di dalam masyarakat yang bertentangan dengan strata kelas yang mapan, individualistik dan kapitalistik sehingga membentuk ketidakberdayaan masyarakat miskin itu sendiri. Karenanya, para pendatang yang selalu memenuhi Jakarta setelah Idul Fitri, jangan berharap akan sukses dan maju dalam kehidupan, bila mental miskin sebagai akar budaya kemiskinan masih diadopsi.
Ratu Selvi Agnesia