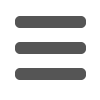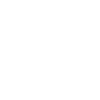Ikhtiar Meredam Paham Radikal

AKARPADINEWS.COM | ALI Imron dan Umar Patek, dua narapidana Bom Bali I tahun 2002 yang menewaskan 202 orang, tak hanya menghabiskan waktunya menjalani hukuman di penjara.
Namun, keduanya punya tugas. Menjadi "praktisi" terorisme yang dilibatkan dalam program deradikalisasi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).
Senin, 25 April lalu, Imron dan Patek dihadirkan sebagai pembicara seminar bertajuk: "Generasi Penerus Bangsa Bersinergi Mendukung Program Pemerintah: Dalam Rangka Kontraradikal dan Deradikalisasi demi Mencegah Instabilitas serta Menjaga Keutuhan NKRI" yang digelar Resimen Mahasiswa Mahasurya, Malang, Jawa Timur. Seminar itu juga menghadirkan pembicara Jumu Tuani, mantan panglima Operasi Pusat Komando Jihad Maluku (PKJM).
Dalam seminar itu, Imron, bekas anggota kelompok radikal, Jemaah Islamiyah (JI) menyatakan sikapnya yang menentang cara kekerasan yang dilakukan militan Islamic State of Iraq and Al-Sham (ISIS) atau Islam State (IS).
Dia pun menegaskan, JI tak ada sangkut pautnya dengan aksi terorisme yang dilakukan ISIS selama ini. Imron lalu mengimbau kepada para pengikut JI, tidak terprovokasi dan berangkat ke Suriah dan Irak untuk berjihad bersama ISIS.
"Jangan termakan slogan dan apapun yang ada di internet," ujar terpidana seumur hidup itu. Di Indonesia, kata dia, lebih banyak kebaikan yang bisa dilakukan daripada ke Suriah dan Irak.
Imron pun mengingatkan pemerintah agar tidak zalim terhadap umat muslim, termasuk melakukan korupsi, karena bisa memicu aksi kelompok radikal. Imron, adik terpidana mati Bom Bali I dan II, Ali Ghufron alias Mukhlas, ditangkap di Pulau Brukang, Kalimantan Timur tahun 2003. Dalam peristiwa bom Bali I tahun 2002, dia tugasnya menyiapkan bom mobil.
Imron mengaku, awalnya menentang rencana pengeboman itu. Namun, dia mengaku, sulit menolak lantaran yang memerintahkannya adalah kakaknya. Ghufron juga yang mengajak Imron untuk berperang ke Afganistan. Karena merasa bersalah, Imron berkali-kali meminta maaf kepada korban dan keluarganya.
Sementara Patek, berbicara tentang kemanusiaan. Atas nama kemanusiaan, Patek alias Hisyam bin Ali Zein alias Ale, siap membantu Pemerintah Indonesia membebaskan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok separatis Abu Sayyaf, di Filipina bagian selatan.
Patek yang dikenal sebagai pengatur serangan bom Bali I, merasa mampu membebaskan sandera karena sangat mengenal Abu Sayyaf. "Aku sangat mengenal Abu Sayyaf dan kelompoknya, sehingga aku rasa sangat mampu membantu," katanya.

Patek bersedia menawarkan bantuan, tanpa motif untuk mendapatkan remisi. "Sama sekali tidak ada. Semuanya tanpa syarat. Ini semua berangkat dari rasa kemanusiaan. Karena hal ini (penyanderaan) mengusik perasaanku," ujarnya.
Patek pernah menjadi komandan pelatihan JI di Mindanao, Filipina. Pengalamannya dalam mengatur strategi bertempur, didapat dari kamp militan al-Qaeda di Afghanistan pada pertengahan 1990-an.
Menurut Nasir Abbas, mantan kepala Mantiqi III JI, Patek pernah dikirim ke Mindanao pada tahun 1995 untuk menggantikannya, melatih militan Front Pembebasan Islam Moro (MILF).
Karena memiliki hubungan dekat dengan MILF, usai melancarkan serangan bom Bali I, di awal tahun 2003, Patek bersama Dulmatin, bersembunyi di Filipina bagian selatan. Keduanya mendapat perlindungan MILF sampai tahun 2004.
Namun, keberadaan mereka sempat terancam saat ada pembicaraan damai antara MILF dengan pemerintah Filipina. Patek dan Dulmatin lalu keluar dari wilayah MILF dan mencari perlindungan ke kelompok Abu Sayyaf di Sulu, awal tahun 2005 hingga 2008-2009.
Selama di Filipina, Patek dan Dulmatin, terlibat serangkaian aksi pengeboman. Patek juga dinyatakan terlibat dalam serangan terhadap gereja-gereja pada malam Natal tahun 2000 dan mengorganisir pengeboman Kedutaan Besar Australia di Jakarta, 9 September 2004.
Patek yang disebut-sebut sebagai mesin pembunuh (killer machine) menjadi target aparat keamanan Filipina, termasuk Amerika Serikat (AS), Australia, dan Indonesia. AS pernah menjanjikan hadiah sebesar US$1 juta kepada siapa saja yang bisa menangkap Patek atau memberikan informasi seputar keberadaannya. Pelarian Patek berakhir di Kota Abbotabad, Pakistan, 25 Januari 2011 lalu.
Kini, Patek yang divonis 20 tahun penjara, mengukuhkan janjinya untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesetiaan itu juga diperlihatkannya saat menjadi pengibar bendera Merah Putih pada upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 20 Mei 2015 lalu.

Namun, belum terlihat pandangan radikal terkikis di benak Patek. Dia memang menentang teror yang dilakukan ISIS di Indonesia. Namun, Patek masih membenarkan cara-cara kekerasan sebagai perjuangan dalam membela kepentingan umat Islam dan tidak dilakukan di Indonesia.
Tak mudah memang mengubah keyakinan ideologis seseorang. Butuh proses dialog yang cukup panjang. Apalagi, referensi paham-paham radikal begitu dominan merasuk dibenaknya sehingga dapat menjadi filter untuk menghalau penetrasi paham-paham yang mereduksi ideologinya.
Pernyataan Patek itu juga menjadi pesan jika tindakan radikal menjadi opsi yang ditempuh untuk membela umat Islam yang dizalimi. Dengan kata lain, kaum radikal tidak akan berhenti melakukan perlawanan, selama umat Islam di sebuah negara, terus-terus mengalami penindasan.
Cara itu diarahkan sebagai upaya memulihkan kondisi umat Islam yang abnormal menjadi kembali normal. Kondisi abnormal itu akibat tindakan destruktif yang dilakukan negara-negara barat terhadap negara-negara Islam.
Sikap Patek itu sifatnya naluriah seorang manusia. Dan, hak setiap umat muslim untuk membela saudaranya sesama muslim yang mengalami penindasan. Tentu, cara-cara yang ditempuh tidak harus melabrak hukum dan menambah banyak korban berjatuhan. Karena, setiap manusia terikat oleh nilai-nilai yang dianutnya. Mereka juga akan melakukan perlawanan dan membantu orang-orang yang sejalan dengan keimanannya kala menghadapi tekanan dari pihak luar.
Keterlibatan Imron dan Patek dalam program deredikalisasi patut diapresiasi. Namun, apa mungkin keduanya yang dikenal sangat radikal, kini berubah lebih humanis dan menentang cara-cara barbar?
Agaknya, sulit memastikan, pandangan dan sikap seseorang, sejalan dengan perilakunya. Secara lisan menentang radikalisme, namun sikap yang terpatri dalam benaknya, membenarkan cara-cara radikal dalam mengubah kondisi yang diharapkan.
Dan, bisa jadi, setelah menghirup udara bebas, mereka pun kembali ke kelompoknya lantaran keberadaannya terisolasi di kehidupan bermasyarakat. Kegagalannya beradaptasi, membuatnya terasing sehingga akan mencari individu lain atau kolega lamanya yang senafas dengan ideologi dan pandangan hidupnya.

Yazid Safaat misalnya. Dia adalah pakar senjata biologis al-Qaeda. Dia sempat mengikuti program deradikalisasi dan dinyatakan berhasil oleh otoritas Malaysia. Lalu, dia bebas setelah mendekam tujuh tahun di penjara.
Namun, Safaat ditangkap lagi pada 8 Februari 2013 lantaran diketahui merekrut warga Malaysia untuk misi bunuh diri di Suriah. Itu menunjukan tidak ada jaminan mantan narapidana yang mengikuti program deradikalisasi benar-benar insyaf untuk tidak terlibat dalam aktivitas terorisme.
Deradikalisasi akan sulit berhadapan narapidana terorisme yang sangat kuat ideologinya, yang menyakini cara-cara kekerasan, hingga mengorbankan rela mengorbankan jiwa dan raganya, sebagai bentuk jihadnya dalam memperjuangkan Islam.
Deradikalisasi pun sulit jika berhadapan dengan individu yang merasa paling benar, egois, cenderung meremehkan orang lain, individualistik, dan sebagainya. Karakteristik narcisistik itu sulit ditaklukan karena yang bersangkutan telah kehilangan rasa empatinya.
Belum lagi tudingan penghianat dan murtad yang dilancarkan mantan kolega lamanya yang masih berkutat dalam aktivitas terorisme. Termasuk, ancaman untuk membunuh dirinya maupun keluarganya jika menyimpang dari ajarannya.
******
Tindakan radikal bukan tanpa motif dan sebab. Rangkaian serangan terorisme pada dasarnya menebar pesan kepada pemerintah, aparat keamanan, dan khalayak luas. Pelaku teror sengaja menciptakan ketakutan sosial agar pesannya direspons atau sekadar memperingatkan eksistensinya.
Radikalisme memiliki tujuan yang jelas dan terencana. Motifnya bisa bersifat politis, ideologis, atau keinginan untuk mendorong perubahan sosial dan politik yang diharapkan.
Cara-cara itu dapat direspons dengan kontra terorisme, yang tidak sekadar dengan cara-cara represif. Namun, dibutuhkan upaya deredikalisasi, dengan tujuan mereduksi paham radikal yang diyakini seorang, termasuk menghalau penetrasi paham-paham radikal ke individu-individu lainnya.
Namun, deradikalisasi bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan waktu dan prosesnya harus berlangsung terus menerus. Individu atau kelompok yang menjadi target deradikalisasi harus diintervensi lewat dialog-dialog rasional, yang berbasis nilai-nilai agama agar bisa menyakinkannya jika pandangan, sikap, dan keyakinannya yang menghalalkan cara-cara kekerasan adalah suatu kesalahan, bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Deradikalisasi sebagai suatu proses yang kompleks, tidak cukup diterapkan dengan cara-cara mengisolasi dan mengawasi pelaku. Namun, mengutip pendapat Petrus Reinhard Golose, dalam bukunya "Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput (2009), deradikalisasi membutuhkan pendekatan multidisplin, mulai dari aspek hukum, psikologi, agama, maupun sosial budaya.
Dalam konteks ini, dibutuhkan model intervensi yang tepat, hingga menyentuh aspek psikologis dan ideologis. Tidak sekadar menyakini perubahan dari sikap dan pandangannya. Namun juga perilakunya. Untuk itu, perlu cara-cara dialog yang intens dengan tujuan mengembalikan rasionalitas pelaku, menyakinkannya, jika cara-cara yang dilakukan itu salah dan merugikan citra agama yang dianutnya.
Program deradikalisasi itu bisa diimplementasikan dalam bentuk dialog lintas budaya dan agama, mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi, kerjasama penanggulangan terorisme, filteralisasi informasi radikal, penguatan peraturan dan perundang-undangan, rehabilitasi, penyebaran informasi, dan sebagainya.

Upaya deradikalisasi yang dilakukan BNPT patut diapresiasi. Keterlibatan para narapidana teroris dalam program deradikalisasi merupakan indikasi keberhasilan program tersebut. Namun, apakah cukup efektif upaya deradikalisasi itu?
Faktanya, beberapa mantan narapidana terorisme, setelah bebas justru makin menggila. Penjara yang seharusnya dijadikan tempat bagi mereka menjalani deradikalisasi, gagal mengubah pandangan, sikap, dan perilaku radikalnya.
Adalah Bahrun Naim, yang disebut-sebut sebagai dalang penyerangan di kawasan Thamrin, Sarinah, Jakarta. Mantan narapidana itu produk gagal atau tidak tersentuh program deradikalisasi. Bahrun yang tidak diketahui keberadaannya, pernah divonis 2,5 tahun penjara karena terbukti memiliki senjata ilegal.
Dugaan keterlibatannya dalam serangan Sarinah, 14 Januari lalu, menunjukan hukuman dan pembinaan di penjara gagal tidak membuatnya jera. Bahkan, Bahrun perannya makin brutal. Dia disebut-sebut anggota militan kelompok radikal ISIS yang berambisi menjadi pemimpin ISIS di kawasan Asia Tenggara.
Mantan narapidana lain yang kembali kumat melakukan aksi terorisme adalah Abdullah Sunata. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 27 April 2011 lalu, memvonisnya 10 tahun penjara karena terlibat aksi terorisme. Hukuman itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntutnya 15 tahun penjara.
Sunata sebenarnya telah dua kali masuk penjara karena terlibat aksi terorisme. Dia pernah divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mei 2006 lalu, karena terbukti menyembunyikan gembong teroris, Noordin M Top dan menguasai senjata api untuk kegiatan terorisme.
Selain gagal melakukan deradikalisasi, penjara juga diduga menjadi pusat pengendalian aksi teror. Adalah Toni Togar, pemimpin kelompok Mujahidin Indonesia yang disebut-sebut mengendalikan rangkaian aksi teror dari penjara.
Toni adalah narapidana pengeboman gereja malam Natal tahun 2000 di Pekanbaru, Riau. Dia divonis 20 tahun penjara dan kini mendekam di Lembaga Permasyarakatan Siantar.
Toni diketahui turut mendalangi rangkaian kegiatan teroris di Aceh, Bandung, Lampung, dan Medan. Dia adalah alumnus pelatihan militer JI di Afganistan tahun 1995. Dia juga diketahui alumnus Pondok Pesantren Al Islam Ngruki Solo yang dipimpin Abubakar Ba'asyir dan pernah menjadi tenaga pengajar di sana.
Lapas juga menjadi tempat narapidana teroris menebar paham-paham radikal lantaran disatukan dengan terpidana kejahatan lainnya. Penjara digunakan bagi mereka untuk merekrut anggota baru. Misalnya, seperti dari laporan International Crisis Group (2007), di mana kelompok Imam Samudra yang menghuni di Lapas Grobokan, Bali, berhasil merekrut A, H, dan Beni. Beni adalah seorang petugas sipil yang didoktrin paham-paham radikal sehingga menjadi miltan. Lalu, kasus Oman di lapas Suka Miskin, Bandung, yang berhasil merekrut Gema Ramadhan.
Pengawai Lapas seharusnya tidak sekadar mengawasi perilaku narapidana teroris. Namun, mereka memainkan peran penting untuk melakukan counter terorism. Karenanya, dibutuhkan pemahaman mereka tentang model intervensi yang tepat dan kajian multidisplin saat melakukan deradikalisasi selama narapidana menjalani masa tahanan.
Cara-cara represif yang kadang menyerempet pada pelanggaran HAM, nyatanya juga menyuburkan benih-benih radikalisme. Ancaman hukuman mati pun tidak serta merta menyurutkan seseorang melepas doktrin jihad.
Buktinya, setelah terpidana Bom Bali I, Imam Samudera, Amrozi, dan Ali Ghufron divonis mati oleh majelis hakim pengadilan Denpansar, Bali tahun 2003 lalu, tidak menyurutkan aksi terorisme. Bahkan, rangkaian serangan makin brutal. Di tahun 2004, terjadi serangan bom Kedutaan Australia (2004), Bom Bali II (2005), serta Bom Hotel Marriot dan Hotel Ritz Carlton (2009).

Serangan-serangan itu tidak hanya melibatkan anggota JI, organisasi yang juga dikendalikan Imam Samudara, Amrozi, dan Ali Ghufron. Namun juga orang-orang baru yang awalnya bukan penganut Salafi Jihadi.
Usai ketiganya dieksekusi mati, sejumlah orang pun menyemut, mengiringi prosesi pemakamannya. Bahkan, ada beberapa kelompok yang menawarkan tanah untuk dijadikan tempat pemakaman ketiganya lantaran dianggap syuhada.
******
Saat ini, gerakan radikal berubah wujud. Jika sebelumnya jaringan terorisme al-Qaeda, kini radikalisme dilakoni ISIS. Dan, gerakan radikal yang berorientasi global itu sudah merambah ke Indonesia.
Setidaknya, serangan di Sarinah, Jakarta, 14 Januari lalu, menguatkan indikasi jaringan ISIS telah merambah ke Indonesia. ISIS memanfaatkan jaringannya di sejumlah negara untuk menebar teror sebagai strategi menancapkan pengaruhnya di negara-negara yang menjadi targetnya.
Paham-paham radikal pun disebar via dunia maya. Lewat Youtube mereka menebar misi dan visinya, target atau sasarannya. ISIS juga memiliki akun twitter yang disadurkan dalam berbagai bahasa agar dapat dibaca dan dipahami banyak kalangan.
Agar proses transformasi ide-ide radikalisme dapat menohok di benak khalayak, mereka pun menggunakan CD, DVD, poster, pamflet, dan media propaganda lainnya di internet. IS juga memiliki Al Hayat Media Center, yang dijadikan sarana menebar proganda radikalisme dengan menggunakan bahasa Inggris, Jerman, Rusia, Prancis, dan sebagainya. Dengan memanfaatkan internet, jaringan IS pun meluas.
Serangan yang terjadi di kawasan Sarinah, Jakarta, 14 Januari lalu, menunjukan militan ISIS merambah ke Indonesia dan siap mati demi mengukuhkan eksistensinya. Militan itu hadir di tengah keramaian dan memperlihatkan aksi nekatnya: membunuh dan melukai korban, dan rela terbunuh atau membunuh dirinya sendiri dengan mengatasnamakan jihad.
Keterlibatan ISIS dalam serangan itu diperkuat oleh klaimnya yang mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Dalam pernyataannya, ISIS menegaskan, sekelompok militan "khalifah" di Indonesia, Jakarta, menargetkan aparat keamanan yang melawan ISIS.
Dalam serangan pertama ISIS di Indonesia itu, lima pelaku dan dua warga sipil tewas. Belasan korban lainnya terluka. Kepolisian Daerah Metro Jaya mengidentifikasi pentolan ISIS yang mendalangi penyerangan itu bernama Bahrun Naim. Indonesia juga diduga menjadi incaran ISIS. Pasalnya, otoritas Turki menahan 16 warga negara Indonesia (WNI) lantaran diduga akan bergabung dengan ISIS.

Laporan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyebut, nama-nama WNI yang ditahan itu antara lain: Ririn Andrian Sawir, Qorin Munadiyatul Haq, Nayla Syahidah, Jauza Firdaus Nuzula, Ikrimah Waliturohman, Alya Nur Islam, Agha Rustam Rohmatullah dan Abdurahman Umarov. Lalu, Tiara Nurmayanti Marlekan, Syifa Hidayah Kalashnikova, Daeng Stanzah, Ifah Syarifah, Ishaq, Asiyah Mujahidah, Aisyahnaz Yazmin, dan Muhammad Ihsan Rais.
Polri juga merilis nama-nama WNI yang hingga kini belum diketahui keberadaannya di Turki antara lain: Usman Mustofamahdani, Sakinah Syawemitafsir, Hapid Umar Babher, Utsman Hafid, Atikah Hapid, Tsabita Utsman Mahdamy dan Salim Muhammad Atamim. Kemudian, Fauzi Umarsalim, Jusman Army, Ulan Isnuri, Hamara Hafshan, Aura Kardova, Dayyan Akhtar, Hamzah Hafiz, Sorayah Cholid, dan Urayana Afra.
Mereka diketahui melakukan perjalanan wisata ke Istanbul, dengan menggunakan agen perjalanan Smailing Tour. Setibanya di Istanbul, 24 Februari 2015, mereka memisahkan diri dan hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Lantaran ancaman itu, maka deradikalisasi harus lebih intensif. Target yang disasar jangan sebatas para narapidana teroris. Namun, juga khalayak luas. Mantan narapidana teroris bisa dilibat untuk memberikan testimoni dan pengalaman selama terlibat dalam aktivitas terorisme.

Di Indonesia, gerakan radikal memiliki rangkaian sejarah. Benih-benih radikalisme itu muncul sejak awal negara ini merdeka. Radikalisme yang mengatasnamakan agama muncul lantaran ketidakpuasan terhadap pemerintah saat itu. Gerakan radikalisme mengatanamakan agama itu dilakoni Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
DI/TII yang dipimpin Maridjan Kartosoewirjo dideklarasikan 7 Agustus 1949. Kartosoewirjo dan Presiden Soekarno awalnya bersahabat. Keduanya sama-sama berguru dengan Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto, pendiri Syarikat Islam (SI).
“Kartosuwiryo di tahun 1918, ia seorang kawanku yang baik. Kami bekerja bahu-membahu bersama Pak Cokroaminoto, demi kejayaan tanah air. Di masa tahun 1920-an di Bandung, kami tinggal bersama, makan bersama, bahkan mimpi bersama-sama," kenang Soekarno dalam buku bertajuk: Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa, Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66, karya H Maulwi Saelan (2001).
Namun, Soekarno-Kartosuwiryo pecah kongsi lantaran perbedaan ideologi. “Aku bergerak dengan landasan kebangsaan, dia (Kartosuwiryo) berjuang semata-mata menurut azas agama Islam," terang Soekarno.
Sampai-sampai, menurut pengakuan Soekarno, pada tahun 1950, Kartosuwiryo mengeluarkan fatwanya, “Bunuh Soekarno! Dialah penghalang pembentukan Negara Islam."
Soekarno pernah menuding Kartosuwiryo berupaya membunuhnya saat acara di Pengguruan Cikini, Jakarta, tempat anak tertuanya sekolah. Pada pukul 20.55, saat turun tangga gedung, meninggalkan acara itu, tiba-tiba granat meledak.
Soekarno berhasil selamat setelah dilindungi pengawalnya. Namun, puluhan anak-anak dan ibu-ibu menjadi korban granat itu. “Itu pekerjaan orang-orang fanatik agama, pengikut Kartosuwiryo," tuding Soekarno. Setelah kejadian itulah, Soekarno menyimpan amarah terhadap Kartosuwiryo.
Kartosuwiryo yang dikenang sebagai pemimpin DI/TII yang misinya memperjuangkan pembentukan negara Islam Indonesia, hidupnya berakhir tragis. Dia tewas dieksekusi regu penembak lantaran menentang Pancasila yang dinilainya sekuler.

Sejarah kelabu itu diyakini berpengaruh dengan aksi radikalisme di Indonesia. Tanggal 5-7 Agustus 2000 lalu, ribuan orang berkumpul di Yogyakarta. Mereka datang dari 24 propinsi untuk mendeklarasikan terbentuknya organisasi Islam militan yang berjuang mewujudkan Imamah (khilafah) yang bernama Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).
Tegaknya syariat Islam merupakan harga mati yang tak bisa ditawar MMI. MMI menyerukan gerakan kembali kepada Al-Quran dan Hadis, dengan mengangkat isu radikal seperti Daulat Islamiyah, Syariat Islam, antibarat, antizionis dan antidemorkasi.
Mereka memimpikan kejayaan dunia Islam masa lalu yang dipandang sebagai zaman keemasan (golden age) dunia Islam, merujuk piagam Madinah sebagai justifikasi pandangannya.
Dalam perjalanannya, organisasi yang diketuai Ustad Abubakar Ba’asyir itu bergerak dengan semangat militansi dan tidak mengenal kompromi. Saat era reformasi bergulir, MMI bersama ormas Islam lainnya mendesak syariat Islam diberlakukan.
Desakan itu pernah mereka suarakan saat sidang Istiwewa MPR 1999, 2000, 2001 dan 2002–saat konstitusi negara sedang diamandemen. Gerakan radikalisme pun semakin mengerkah ketika banyak negara-negara Islam menderita akibat invasi militer AS dan sekutunya. MMI melakukan razia warga negara asing khususnya warga AS. MMI pun pernah dituding terlibat dengan jaringan Al-Qaeda.
Titik Lemah RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Radikalisme harus senantiasa menjadi perhatian serius. Jangan sampai, aparat terus-terusan kebobolan. Terlebih ketika organisasi ini mulai berkembang, tidak lagi bersifat lokal, melainkan lintas negara. Gerakan mereka semakin terorganisir, baik secara teknis, perlengkapan, maupun dukungan finasial.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dan DPR adalah merevisi Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Meski semangatnya memerangi terorisme, draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus memperhatikan dampak dan efektifitasnya dalam memangkas akar terorisme.
Dalam proses pembahasannya, draf RUU tersebut menuai sorotan kalangan masyarakat sipil. Pasalnya, selain tidak efektif memberantas terorisme, RUU itu juga berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Kritik itu disampaikan Koalisi masyarakat sipil yang terdiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Imparsial, Institue for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers di Jakarta, Jum'at (29/4).

Beberapa poin krusial yang disoroti di antaranya potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). RUU itu juga melabrak KUHAP lantaran memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menangkap seseorang orang yang menjadi terduga melakukan pidana terorisme dalam waktu 30 hari.
Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengatur prosedur penangkapan dan penahanan, dapat dilakukan dalam waktu satu hari hanya kepada tersangka berdasarkan bukti yang cukup.
Koalisi juga mempersoalkan sanksi berupa pencabutan status kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang ikut pelatihan terorisme. Ketentuan itu konstitusi seperti diatur dalam Pasal 28D UUD 1945. Pencabutan kewarganegaraan menyebabkan tidak adanya jaminan perlindungan dari negara.
Koalisi juga mempertanyakan ketentuan yang menempatkan seseorang di sebuah tempat tertentu selama enam bulan dalam rangka deradikalisasi. Cara-cara isolasi itu dikhawatirkan rentan penyiksaan.
Akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan terorisme juga dipersoalkan. Karena, fakta mengurai, tidak ada mekanisme akuntabilitas saat dilakukan pencegahan, penangkapan, dan penahanan terhadap terduga teroris.

Seringkali terjadi kasus salah tangkap. Bahkan, ada yang berakibat kematian seperti kasus Siyono yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terdapat dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Densus 88 dalam penanganan terduga teroris asal Klaten itu.
Komnas HAM menemukan tanda-tanda kekerasan berupa patah tulang rusuk di dada Siyono. Komnas HAM juga menyimpulkan tidak ada tanda-tanda perlawanan yang dilakukan Siyono karena tidak adanya bekas luka di tangannya. Fakta-fakta tersebut membantah klaim pihak kepolisian yang menyebut Siyono melakukan perlawanan.
Kasus Siyono merupakan pengulangan yang pernah terjadi sebelumnya. Dari data yang dimiliki Komnas HAM, sebanyak 121 orang yang diduga melakukan terorisme, tewas, tanpa menjalani proses peradilan (extrajudicial killing). Selama ini, publik tidak mengetahui pertanggungjawaban pelaksanaan operasi pemberantasan terorisme yang terkesan tertutup.
Aktivis PSHK Miko Ginting menilai, RUU ini lebih menggunakan pendekatan perang ketimbang pendekatan hukum. "RUU ini lebih kepada pendekatan perang, dalam beberapa pasalnya," tegasnya,
Penanganan terorisme juga mengabaikan tuntutan ganti kerugian jika terjadi salah sasaran. Kerugian yang dialami korban maupun pihak terdampak lainnya, tentu bukan hanya sebatas kerugian materil. Namun, juga kerugian imateril, seperti trauma psikis, stigma teroris terhadap korban salah tangkap, dan sebagainya. Draf RUU itu dinilai belum membahas tentang penggantian kerugian itu.

Aktivis ICJR, Erasmus Napitupul menilai, RUU itu tidak membicarakan tentang korban. Kompensasi dan rehabilitas, belum menjadi perhatian. RUU itu juga kurang mendapatkan perhatian khusus bagi para korban, mulai bantuan medis psikologis sampai hal yang menyangkut kompensasi.
Untuk kompensasi, dari pengadilan tindak pidana terorisme yang digelar, hanya dalam kasus JW Marriot, hakim memerintahkan pemberian kompensasi bagi korban. Seharusnya, kompensasi itu segera diberikan tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Koalisi mendesak DPR membuka ruang partipasi publik dalam pembahasan RUU tersebut.
M. Yamin Panca Setia