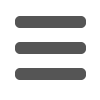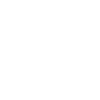Dimensi Ketuhanan dan Kemanusiaan di Tengah Pusaran Budaya

Bang Sém
Di mana posisi nilai Ketuhanan dan kemanusiaan dalam kehidupan personal dan sosial kita kini?
Masihkah berada pada tempat yang kita sakralkan, yakni: relung sukma, yang memungkinkan menggerakkan seluruh instrumen spiritual dan kemanusiaan kita (nalar, naluri, rasa, dan indria) untuk segera kembali ke garis azimut perjalanan panjang menuju tujuannya: bahagia dan bebas petaka?
Jangan-jangan kita sudah terlalu jauh melenceng ke luar orbit dan tak peduli lagi, karena asyik bersoal tentang perbedaan insaniah, dan karena itu memandang penting demokrasi sebagai cara bertarung memperebutkan kekuasaan. Lantas tak lagi peduli dengan prinsip-prinsip keadilan personal dan sosial.
Lantas, asyik bermain-main di kubangan dehumanitas dan yang menempatkan diri kita sebagai manusia-manusia ragawi yang membebaskan pikiran terbang bebas, sembari membebaskan sukma atau jiwa ngembara sesuka hati ke mana saja di hendak pergi.
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tiba-tiba mengusik, kala beragam media, termasuk media sosial - tanpa salam, masuk ke dalam smartphone dalam genggaman, mengirim kabar tentang jatuhnya begitu banyak korban manusia dalam berbagai peristiwa yang terjadi belakangan hari, di tanah air kita.
Bagaimana mungkin bisa terjadi di tanah air, di suatu bangsa, yang (konon) dimuliakan di masa lalu karena keluhuran budinya, bisa terjadi perampasan nyawa manusia dengan cara yang tidak manusiawi.

Bagaimana mungkin bisa terjadi di tanah air, di suatu bangsa, kekerasan dan anarkisme bisa terjadi dengan sangat mudah, dan dipergunakan sebagai 'cara' mengelola perbedaan gagasan, sikap, serta tindakan untuk dan atas nama pemuliaan atas hak asasi manusia (personal, komunal, dan sosial) yang menjadi jargon harian kehidupan sehari-hari.
Bagaimana mungkin bisa terjadi di tanah air, di suatu bangsa, yang dibangun dengan spirit sosio religius, humanitas, pluralisme dan multikulturalisme, populisme, dan sosio justice, ghibah - buhtan - dan fitan (rumors, hoax, dan fitnah) terbiarkan begitu saja meletupkan friksi, konflik, dan kemudian deformasi kultural, hanya karena ketidak-mampuan kita memelihara reformasi sebagai jalan perubahan yang memang melelahkan?
Jangan-jangan kita, sedang membiarkan diri, hanyut oleh arus besar, pusaran zaman yang sedang bergerak semakin jauh dan sangat berjarak dengan minda dan jiwa ke-Indonesia-an, yang bertumpu di atas kesadaran kebangsaan, keagamaan, dan kecendekiaan.
Sungguhkah situasi dan kondisi mutakhir tanah air kita sedang menjelaskan dengan gamblang dan terang benderang, bangsa ini sungguh sedang kehilangan kaum elite, kaum khashshash -- enlighter -- yang posisinya diambil alih oleh meningkatnya jumlah petinggi di berbagai lapangan kehidupan?
Karenanya, kita miskin negarawan (statesman), miskin wiseman - scholars, miskin intelektual, dan miskin budayawan?
Mendahulukan Alasan
Dua pekan terakhir, saya mengikuti beberapa diskusi menarik tentang nilai adab dan keadaban dan dimensi budaya yang raib.
Diskusi itu berlangsung mulai dari sudut halaman belakang Taman Ismail Marzuki, 'Gedung Rektorat' - kampus Universitas Indonesia - Depok, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, kantor Majelis Adat Aceh, kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, kantor Dinas Kebudayaan Bali - Renon - Denpasar, dan kampus Universitas Padjadjaran - Jl. Dipati Ukur - Bandung.

Dalam diskusi-diskusi, itu mengemuka beragam pemikiran, yang -- intinya -- menyatakan: negara terlalu sering hadir dan tak hendak beranjak dari ruang politik, ekonomi, keamanan, dan ruang publik dengan beragam ritual yang menjadi pusat perhatian media. Namun, negara absen di ruang - ruang kebudayaan yang berpengaruh langsung atas kerontangnya dimensi peradaban, khasnya kemanusiaan dan keadilan. Kalaupun hadir di ruang-ruang tersebut, sifatnya cenderung formal dan nyaris tanpa ruh. Itu pun lebih terpusat pada upacara-upacara eksibisi kesenian dan ritual, yang bertumpu pada wilayah artistik dan estetik, dan tetap berjarak dengan wilayah etik.
Negara -- melalui penyelenggara pemerintahan -- absen di ruang-ruang kebudayaan dan peradaban yang ditopang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, yang memberi peluang pada kerjasama (bukan kerja bersama apalagi sama-sama kerja) melalui pengakuan, pemahaman bersama, regulasi keanekaragaman dan heterogenitas yang banyak menyerap aspirasi (termasuk ketidakpuasan dan divergensi cara pandang).
Terutama karena terlalu sibuk bermain-main dengan sesanti, jargon-jargon, dan simbol-simbol tentang kebersamaan tetapi tidak menghasilkan kesamaan. Sibuk dengan keberbagaian dan keberagaman, dan abai pada persatuan dan persamaan.
Secara retoris persamaan dan persatuan kerap diucapkan, sembari kerap nampak ketidakpahaman dan ketidakmampuan petinggi mengenali sifat dan watak masyarakat yang memang heterogen.
Pembicaraan dalam rangkaian diskusi itu melihat retorika dan sikap yang diperlihatkan para petinggi, menggambarkan keadaan darurat budaya. Melalui berbagai pernyataan resmi dan tidak resmi, terkesan terlalu banyak petinggi yang mengalami ambivalensia, keterbelahan dalam melihat dan menghampiri persoalan dalam kehidupan nyata masyarakat sehari-hari.
Keterbelahan yang disebabkan oleh tidak integral-nya nalar, naluri, rasa, dan dria, sebagai satu kesatuan yang utuh. Muaranya adalah praktik demokrasi, tidak seperti dipikirkan para pendiri republik 74 tahun lalu. Yakni, demokrasi sebagai cara mencapai harmoni kebangsaan, dengan menyediakan jiwa bangsa (l'âme de la nation) sebagai tempat nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan abadi dan berkembang.
Beragam produk undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan bagian kecil saja dari semangat pemajuan kebudayaan, baru mengacu pada hal-hal yang relatif masih terlalu dipahami secara homogen.

Keragaman dan perbedaan belum dianggap sebagai kekuatan pendorong kebijakan governansi (tatakelola) negara secara visioner, sebagai upaya mempersiapkan masa depan lebih baik. Akibatnya, pembangunan yang diselenggarakan dengan menyebut serta sustainabilitas, keberlanjutan, masih tergantung pada bagaimana dan di mana kita berbicara. Akibatnya terjadi diskriminasi dan disparitas yang nyata sosoknya, tapi nyaris tak terlihat dan tersentuh dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Pembuat kebijakan menyadari adanya diskriminasi itu, tetapi mungkin melupakannya terlalu cepat pada saat keputusan dan pilihan perangkat kebijakan diambil. Terkesan, para penyelenggara negara dan pemerintahan dan para petinggi politik -- termasuk petinggi organisasi kemasyarakatan, mengabaikan aspirasi dan enggan berkomitmen sebagaimana mestinya.
Bahkan berkembang kesan, kuatnya keengganan untuk berurusan dengan realitas ketidaksetaraan, diskriminasi, dan hierarkisasi di berbagai tempat. Hasilnya, berlakulah berbagai kebijakan tanpa kepedulian untuk menjawab dengan sangat konkret berbagai pertanyaan dan aspirasi dari warga negara yang peka, sehingga memicu bergeraknya generasi baru untuk mewakili suara mayoritas rakyat yang terabaikan.
Berbagai pernyataan petinggi negara dalam merespon realitas pertama kehidupan sosial -- sebutlah : kerusuhan Wamena, demonstrasi massal Mahasiswa di berbagai kota di seantero tanah air, serta bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan -- cenderung sangat reaktif. Mendahulukan intuitive reason - alasan-alasan pembenaran, katimbang cara (way) dalam mengatasi masalah. Terutama ketika persoalan-persoalan yang mengancam terjadinya dehumanitas bergerak sangat cepat.
Para petinggi, melalui berbagai argumen dalam pernyataan mereka, lebih banyak memberikan alasan. Padahal yang diperlukan rakyat adalah cara mengatasi dan menyelesaikan masalah.
Saatnya Negara Hadir di Lapangan Kebudayaan
Berbagai pemikiran yang berkembang di forum-forum diskusi khas kebudayaan yang saya ikuti, mencermati dengan tajam dan jernih, bagaimana negara gagap dalam menghampiri hubungan masyarakat terkait dengan keragaman komunitas (antara individu dan kolektif). Lalu, cenderung menyimpan kegagapannya, itu di bawah 'karpet sejarah,' tanpa menyadari, kelak akan menjadi persoalan di masa depan.

Ketegangan-ketegangan yang muncul kini, setidaknya dalam separuh dekade terakhir, merupakan isyarat, ada berbagai persoalan yang disimpan di bawah 'karpet sejarah,' kini terkuak. Misalnya, ihwal rasisme, pun janji-janji yang tak terpenuhi di masa lampau dengan tumpukan kekecewaan, ketika ide-ide dan proposal baru penyelesaian masalah dihadapkan dengan realitas sosial, politik dan sosiologis, yang kemudian dikuatirkan akan menambah lagi kekecewaan baru di masa kini dan nanti.
Di sinilah, diperlukan kesadaran dimensional Ketuhanan dan kemanusiaan, yang selalu menerbitkan iren (pemikiran segar prediktif, kritis, dan khas) sebagai instrumen menghapus potensi ketegangan dibandingkan dengan pikiran politis (strategis maupun pragmatis) diperlukan untuk mencegah meletupnya konflik.
Kita memerlukan irenitas untuk mengelola perdebatan dalam mempertemukan persamaan pemikiran dan sikap melalui musyawarah aktif semua kalangan untuk kontribusi ini. Sekaligus mencapai mufakat.
Setarikan nafas, irenitas diperlukan pula untuk menerima fakta tentang perbedaan (melalui muzakarah) yang memperkaya referensi dalam mengidentifikasi ketegangan dan kontradiksi yang dapat mendasari munculnya model baru kebijakan budaya dalam melakukan intervensi publik. Khasnya dalam menghidupkan tanggung jawab kolektif seluruh kalangan sebagai mitra publik dan profesional di tengah masyarakat overproduksi simbolis.
Terutama kini, ketika kita sedeang getun dengan model intervensi publik di tengah era ekonomi yang kontroversial, seperti dikatakan Bernard Stiegler (2015), karena percepatan teknologi informasi dan komunikasi.
Sekaranglah saatnya negara hadir di lapangan kebudayaan dengan merumuskan gagasan-gagasan jernih sebagai pondasi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Dimulai dengan memerlihara ruang yang tepat bagi pengembangan dan manifestasi nilai Ketuhanan dan kemanusiaan, sebagai cara menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar idiil sekaligus tujuan negara dan bangsa. |